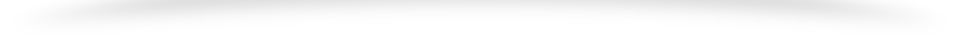Pecihitam.org – Bagi orang-orang yang anti tasawuf alias hanya penggemar ilmu syariat semata, tidak jarang melontarkan tuduhan tak berdasar kepada kaum Sufi. Tuduhan tersebut mengatakan bahwa dalam bertasawuf, kaum Sufi itu anti dengan surga dan tidak takut neraka.
Mereka juga mengatakan bahwa kaum sufi itu gila. Rasulullah Saw saja pernah berharap surga dan dihindarkan dari neraka. Jika Rasulullah saja mencontohkan demikian, mengapa kaum Sufi malah anti dengan surga dan tidak takut neraka?
Tuduhan selanjutnya tentang kaum sufi adalah bahwa tujuan mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak mengharap surga atau neraka, dianggap sebagai akidah yang salah. Kaum pembenci tasawuf lalu mengutip dalil dalam ayat Al-Qur’an, misalnya berikut,
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ
“Makan dan minumlah (di surga) dengan nikmat yang disebabkan oleh amal yang telah kamu kerjakan di hari-hari yang lampau….” (al-Haaqqah, 24) .
Al Quran saja mengatakan demikian, jadi jelas pandangan kaum Sufi bertentangan dengan ayat tersebut. Apa yang katanya kaum sufi itu ternyata tidak paham al Quran dan Hadist?
Agar tidak berlama-lama, mari kita coba menjawab tuduhan tak berdasar tersebut. Memang surga dan neraka disebut berkali-kali dalam Al-Quran maupun Hadits dan tentu saja, itu merupakan janji dan peringatan Allah swt.
Namun perlu digaris bawahi memahami ayat maupun hadits tersebut harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak sekadar tekstualnya saja. Misalnya kata “Takut” disebut beberapa kali bentuk takut dalam Al Quran. Ada yang menggunakan kata Taqwa, Khauf dan ada pula Khasyyah dan lain sebagainya.
Makna takut dengan penyebutan yang berbeda-beda itu pasti memiliki dimensi yang berbeda pula, apalagi dalam responsi psikhologi keimanan seseorang yang pastinya juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga kata Jannah dan Naar, syurga dan neraka.
Penekanan-penekanan kata Naar dalam Al-Quran juga memiliki struktur hubungan yang berbeda tergantung konteksnya. Naar yang disebutkan untuk orang kafir, pasti memiliki penekanan berbeda dengan orang munafik, orang fasik, dan orang beriman yang ahli maksiat.
Itu artinya kata Naar, punya macam-macam makna dan disandarkan ruang neraka: Ada Neraka Jahim, Neraka Jahanam, Neraka Sa’ir, Neraka Saqar, Neraka Abadi, dan penyebutan kata Naar yang tidak disandarkan pada sifat neraka tertentu.
Jika Naar dimaknai secara umum, justru menjadi dzalim, kerana faktanya tidak demikian. Hal yang sama jika para Sufi memahami Naar dari segi hakikatnya neraka, juga tidak boleh disalahkan. Apalagi jika seseorang memahami neraka itu sebagai api yang berkobar. Kalimat Naar tanpa disandari oleh Azab, juga berbeda dengan Neraka belaka.
Misalnya kalimat dalam ayat di surah Al-Baqarah,
“Wattaqun Naar al-llaty waquduhannaasu wal-Hijarah”
dengan ayat yang sering kita baca,
“Waqinaa ‘adzaban-Naar,”
Keduanya memiliki dimensi berbeda. Ayat pertama, menunjukkan betapa pada umumnya manusia, kerana didahului dengan panggilan Ilahi ”Wahai manusia”. Maka Allah langsung membuat ancaman serius dengan menyebutkan kata Naar.
Tetapi pada doa orang beriman, “Lindungi kami dari siksa neraka,” maknanya sangat berbeda. Karena yang kedua ini berhubungan dengan kelayakan keimanan hamba kepada Allah, bahwa yang ditakuti adalah Azabnya neraka, bukan apinya. Sebab api tanpa azab, jelas tidak panas, seperti api yang membakar Ibrahim as.
Oleh sebab itu, jika seorang Sufi menegaskan keikhlasan ubudiyahnya hanya kepada Allah, memang demikian perintah dan kehendak Allah. Bahwa seorang mukmin menyembah Allah dengan harapan surga dan ingin dijauhkan neraka, dengan perpekstifnya sendiri, tentu kelayakan keikhlasannya di bawah ayat yang pertama.
Dalam berbagai ayat mengenai Ikhlas, disebutkan agar kita hanya menyembah Lillahi Ta’ala (karena Allah). Namun jika punya harapan lain selain Allah termasuk di sana harapan surga dan neraka, itu juga diterima oleh Allah. Namun, kelayakannya adalah bentuk responsi mukmin pada surga dan neraka paling rendah.
Semua mengenal bagaimana Allah membangun contoh dan perumpamaan, baik untuk menjelaskan dirinya, surga maupun neraka. Kaum Sufi memilih perumpamaan paling hakiki, karena perumpamaan surga dan neraka yang paling rendah sudah mereka lampaui.
Analoginya seperti kualiti moral seorang pekerja di sebuah kantor yang juga berbeda-beda. Orang yang bekerja hanya untuk mencari uang dan untung, tidak boleh mencaci dan mengecam orang yang bekerja karena mencintai pekerjaan dan mencintai pemimpinnya tersebut. Walaupun sama-sama kerjanya, namun kualiti moral dan dedikasihnya pasti berbeda.
Bagi seorang pemimpin yang bijaksana, pasti ia lebih mencintai pekerja yang didasari oleh motivasi cinta yang luhur pada pekerjaan, perusahaan dan mencintai dirinya, dibandingkan dengan para pekerja yang hanya mencari untung belaka, sehingga mereka bekerja tanpa roh dan spirit yang luhur.
Surga dan neraka pun demikian. Pandangan surga memiliki kelayakan rohani dan spiritual yang berbeda antara Sufi dengan kaum awam biasa. Misal persepsi mengenai bidadari. Bagi kaum Sufi bidadari yang digambarkan oleh Al-Qur’an dan hadist, adalah Tajalli (penampakan) sifat-sifat dan Asma ke-Mahaindah-an Ilahi, dan tentu ini sangat berbeda dengan kaum awam yang membayangkan sebagai kenikmatan biologis seksual hewani.
Surga bagi kaum Sufi adalah Ma’rifatullah dengan darajat kema’rifatan yang berbeda-beda. Kerana nikmat tertinggi di surga adalah Ma’rifat Dzatullah. Jadi kalimat Rabiah al Adawiyah tentang ibadah tanpa keinginan surga adalah gambaran kenikmatan fizik yang selama ini kita persepsikan. Dan hal demikian memang boleh menjadi penghalang (hijab) antara hamba dengan Allah dalam proses kema’rifatan.
Bagi orang beriman yang masih bergelimang dengan hawa nafsu, maka persepsi tentang nikmat surga, kebanyakan pantulan nafsu hewani dan syahwatnya. Kemudain bayangan kesenangan duniawi ingin dikorelasikan dengan rasa nikmat surgawi yang ideal dengan syahwat.
Dari sini Rabi’ah Adawiyah dan para Sufi lainnya ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari segala bentuk dan motivasi selain Allah yang boleh jadi malah akan menghambat perjalanan ma’riftullah. Dengan bahasa seni yang indah dan tajam, para Sufi hanya menginginkan Allah, bukan menginginkan makhluk Allah.
Para sufi pun berdoa,
“Tuhanku, hanya engkau tujuanku, dan hanya ridho-Mu lah yang kucari. Limpahkan Cinta dan Ma’rifat-Mu kepadaku…”
Jadi silahkan direnungkan, apakah kalimat diatas menunjukan bahwa para sufi anti surga dan tak takut neraka? Ataukah karena kesombongan hingga hakikat surga dan neraka pun kau perdebatkan, kemudian melontarkan tuduhan demikian?
Wallahua’lam bisshawab