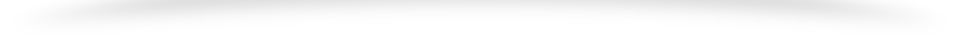PeciHitam.org – Hukum onani dalam islam memang masih diperdebatkan berbagai pihak. Mayoritas ulama fiqih membolehkan onani (istimna’), baik dengan tangan maupun dengan yang lain, bila dilakukan bersama pasangan yang sah, selama tidak ada perkara yang mencegah dari suami atau istri, seperti haid, nifas, puasa, I’tikaf, atau ibadah haji.
Sebab, pasangan adalah tempatnya bersenang-senang dan menyalurkan kebutuhan seksual yang dibenarkan syariat (Lihat: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Daru al-Salasil, 1404 H, jilid 4).
Namun hukum onani dalam islam yang dilakukan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, masih belum jelas. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada pula yang mengharamkan dalam kondisi tertentu, dan membolehkan dalam kondisi yang lain. Namun, ada pula yang memakruhkan.
Adapun para ulama yang mengharamkan adalah ulama Maliki dan Syafi’i. Ulama Syafi’i beralasan bahwa Allah memerintah menjaga kemaluan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapat dari hasil peperangan, sebagaimana ayat Al-Quran yang artinya:
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,” (QS. al-Mukminun, 23:5).
“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. al-Mukminun, 23:6).
Mereka yang keluar dari ketentuan ayat di atas dianggap melampaui batas, melanggar ketentuan Allah, dan keluar dari fitrah, sebagaimana dalam lanjutan ayanya:
“Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. al-Mukminun, 23:7).
Di samping itu, Allah juga memerintah agar yang belum mampu menikah untuk bersabar menahan dorongan syahwat dan keinginan seksualnya hingga Allah memberikan kemampuan dan kemudahan untuk menikah dengan karunia-Nya, Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, (QS al-Nur, 24:33).
Dengan demikian, menurut ulama Syafi’i, onani atau masturbasi merupakan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Hanya saja dosa onani atau masturbasi lebih ringan dosanya dari berzina karena bahayanya tak sebesar yang ditimbulkan perzinaan, seperti kacaunya garis keturunan, dan sebagainya.
Sementara ulama Maliki berargumentasi tentang istimna’ atau hukum onani dalam islam mengharamkan, sesuai dengan sabda Rasulullah:
“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba’at (menikah), maka menikahlah! Sebab, menikah itu lebih mampu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab, berpuasa adalah penekan nafsu syahwat baginya,” (HR Muslim)
Mereka menyatakan, seandainya istimna’ atau onani diperbolehkan oleh syariat, tentu Rasulullah telah menyarankannya sebab onani lebih mudah daripada puasa. Diamnya beliau ini menjadi dalil bahwa onani adalah haram. (Lihat: Syekh ‘Abdurrahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziri, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba‘ah, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 2003, jilid 5).
Adapun hukum onani dalam islam yang mengharamkan dalam kondisi tertentu dan membolehkan dalam kondisi yang lain adalah para ulama Hanafi. Istimna’ diharamkan bila sekadar untuk membangkitkan dan mengumbar dorongan syahwat. Namun, ketika kuatnya dorongan syahwat, sementara pasangan sah tempat menyalurkan tidak ada, sehingga istimna’ semata untuk menenangkan dorongan tersebut, maka hal itu tidak dipermasalahkan.
Bila tidak dilakukan justru ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dengan tujuan sebagaimana dalam kaidah “Meraih kemaslahatan umum dan menolak bahaya yang lebih besar dengan mengambil sesuatu (antara dua perkara) yang lebih ringan bahayanya.”
Bahkan, Ibnu ‘Abdidin dari ulama Hanafi menyatakan wajibnya ismina’ bila dipastikan mampu membebaskan diri dari perbuatan zina. Singkatnya, pendapat para ulama Hanafi ini memiliki dua sisi: pertama boleh karena darurat, dan haram karena masih ada solusi terbaik, yaitu berpuasa.
Sementara pendapat ulama Hanbali sejalan dengan pendapat ulama Hanafi. Menurut ulama Hanbali, istimna’ hukumnya haram kecuali karena mengkhawatirkan dirinya terjerumus kepada perbuatan zina, atau karena takut akan kesehatan, baik fisik atau mentalnya, sedangkan istri tidak ada dan menikah belum mampu. Maka tidak ada salahnya istimna’ baginya.
Bahkan, menurut sebagian ulama Bashrah, yang sudah menikah pun diperbolehkan istimna’ manakala ia berada dalam perjalanan, bukan di tempat tinggal. Sebab dalam kondisi ini, ia diyakini lebih mampu menjaga pandangan dan perbuatan zina.
Terakhir adalah pendapat yang memakruhkan. Ini adalah pendapat Ibnu Hazam, sebagian pendapat Hanafi, sebagian pendapat Syafi‘i, dan sebagian pendapat Hanbali. Istimna’ dimakruhkan karena termasuk perkara yang status keharamannya tidak dijelaskan Allah secara eksplisit. Sehingga ia hanya merupakan akhlak yang tidak mulia dan perangai yang tidak utama. (Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Darul al-Kitab al-’Arabi, 1997, cet. ketiga, jilid 2).
Dari uraian di atas, mayoritas ulama memandang istimna’, baik oleh laki-laki (onani) atau oleh perempuan (masturbasi) sebagai perbuatan tidak terpuji, melampaui batas, dan melanggar fitrah manusia. Tak heran bila ulama Maliki dan Syafi’i mengharamkannya, terlebih jika sudah sampai pada tingkatan yang dapat menjauhkan seseorang dari pernikahan dan berketurunan.
Kendati ada pendapat yang membolehkan hanyalah pintu darurat atau mengambil bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya yang ada. Agar tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan, siapa pun yang telah mampu, terutama kaum muda-mudi, hendaknya segera menikah.
Apabila belum siap, ikutilah tuntunan Rasulullah, yakni dengan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, menghindari hal-hal yang mendorong kepada perilaku tercela dan menyimpang dari fitrah.