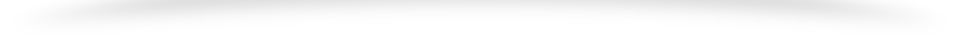Pecihitam.org – Bergulirnya rezim pemerintahan dari orde baru ke era reformasi membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat termasuk kebebasan menyampaikan kritik di Indonesia.
Jika di era orde baru kritik menjadi barang mahal, maka pasca Soeharto ‘lengser keprabon’ yang disusul oleh perkembangan teknologi dan media sosial seperti sekarang ini, siapapun orangnya, di manapun tempatnya dan apapun profesinya bisa dengan bebas menyampaikan kritik secara terbuka bahkan kepada presiden sekalipun. Sesuatu yang hampir mustahil terjadi di Indonesia 30 tahun yang lalu.
Namun seiring dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan menyampaikan kritik yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial di Indonesia, tanpa disadari mulai terjadi pergeseran perilaku kritik di masyarakat.
Dulu, lalu lintas kritik tak pernah terpantau secara langsung oleh publik. Sekarang, kita bisa mengkonsumsi lalu lintas kritik yang terbuka dan terjadi di ruang publik, setidaknya di akun medsos kita.
Hampir setiap hari kita menjadi konsumen aktif media sosial dengan lalu lintas percakapan, termasuk di dalamnya kritik, yang tidak jarang berisi ujaran kebencian, sumpah serapah, fitnah, cacian, makian, sentimen sara yang entah ditujukan kepada perseorangan, publik figur ataupun pemerintah, maka tak heran jika muncul istilah “maha benar netizen atas segala komennya”.
Dalam kondisi tersebut rasa-rasanya penting bagi kita untuk memahami secara mendalam istilah “kritik” serta menengok sebenarnya bagaimana tradisi kritik pendahulu kita utamanya tradisi kritik di dunia Barat dan Islam.
Selain menjadi basis dan fundamen bertindak bagi individu pelaku kritik, pemahaman mendasar terhadap istilah kritik akan membentuk wajah perilaku kritis-etis di masyarakat utamanya masyarakat media sosial agar tidak terjebak pada praktek “hanya sebatas kritik” atau kritik anarkis seperti di atas.
Sebagaimana dijelaskan dengan lugas oleh F. Budi Hardiman dalam bukunya “Kritik Ideologi” bahwasannya kata “kritik” sebenarnya sudah dipakai sejak masa renaisance (1350-1600). Pada masa itu, masyarakat Eropa membangkitkan kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno utamanya untuk tujuan mengusir kegelapan dogmatis warisan abad pertengahan (600-1400).
Dalam konteks tradisi pemikiran kritis di Barat, setidaknya terdapat beberapa corak pemikiran kritis para filsuf dengan berbagai latar belakangnya. Pengajar filsafat di sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya ini menyajikan epic perdebatan dan saling kritik antar beberapa filsuf kenamaan tersebut.
Kritik versi Emmanuel Kant misalnya yang disebut sebagai kritisisme dalam perlawanannya terhadap jalan yang ditempuh oleh filsuf sebelumnya. Kritik versi Emmanuel Kant ini berupaya membongkar dogmatisme dan sahih tidaknya klaim pengetahuan dengan tanpa prasangka.
Menurutnya upaya tersebut hanya bisa dilakukan oleh rasio belaka. Setidaknya kritik versi Kant ini punya tiga kata kunci penting, yang pertama adalah “kritisisme dogma”, yang kedua “tanpa prasangka” dan yang ketiga “rasio”.
Berbeda dengan Kant yang konsen pada kritik terhadap dogma, kritik Hegel lebih bermain pada ranah negasi, dialektika dan refleksi diri yang bermuara pada kesadaran. Hegel menawarkan kritik yang berdiri di atas dasar yang tak tergoyahkan. Ia mengkritik tawaran kritik Kant yang bersifat transcendental.
Sebagai contoh model kritrik Hegel adalah proses penyadaran rasio yang diperoleh dalam revolusi Prancis yang membuat warga Prancis memperoleh kebebasannya dari praktik lingkar kekuasaan monarki absolut.
Setali tiga uang dengan dua corak yang berbeda mengenai kritik di atas, kritik dalam pandangan Karl Marx juga memiliki posisi yang otonom. Menurut Marx, kritik dalam filsafat Hegel masih kabur karena Ia memahami sejarah secara abstrak. Marx punya pandangan lain.
Menurutnya kritik bukan hanya sejarah melainkan praxis, lebih tepatnya praxis revolusioner yang dilakukan oleh kaum proletariat. Ia juga bisa diartikan sebagai upaya mengemansipasikan diri dari penindasan dan alienasi yang dihasilkan oleh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.
Kritik dalam konteks Marx ini tidak hanya melukiskan masyarakat akan tetapi juga membebaskannya. Fragmen di atas menggambarkan betapa perang argumen kritis filosofis adalah hal yang jamak terjadi di kalangan para filsuf Barat.
Lalu bagaimana dengan tradisi kritik dalam dunia Islam? Salah satu epic perdebatan dan saling kritik paling fenomenal dalam dunia Islam tentu perang argument filosofis yang terjadi antara dua begawan filsuf Muslim kenamaan yakni al Ghazali dan Ibnu Rusyd.
Saling kritik tersebut dimulai dengan komentar al Ghazali terhadap al Farabi dan Ibnu Sina. Melalui karyanya Tahafut al Falasifa (Incoherence of the Philosophers) al Ghazali melontarkan kritik tajam terhadap dua Filsuf muslim kenamaan tersebut.
Dalam pandangan al Ghazali penjelasan problem ketuhanan dan alam semesta dua pendahulunya tersebut selain terlalu didominasi oleh peran akal, penjelasan keduaya juga bersifat metafisis dan terlalu spekulatif, masih bernuansa Aristotelian serta tidak sesuai dengan ajaran Qur’an dan hadits yang merupakan sumber otoritatif bagi kaum Muslim.
Kritik al Ghazali tersebut lalu dikritik oleh Ibnu Rusyd dalam bukunya Tahafut al Tahafut (Incoherence of the Incoherence) atau kerancuan berfikir al Ghazali dalam kitab Tahafut al Falasifah. Ibnu Rusyd secara tegas menyetujui penjelasan Aristoteles dan Ibnu Sina mengenai konsep ketuhanan dan alam dengan tetap harus mendialogkannya dengan prinsip-prinsip otoritatif dalam agama.
Jika kita merujuk pada tradisi kritik di kalangan filsuf barat dan filsuf Islam di atas, bisa kita amati bahwasannya kritik para filsuf pendahulu kita selalu dilontarkan dalam bingkai bangunan epistemologis, teoritis dan praksis yang kuat sehingga disamping menyentuh inti persoalan, kritik juga akan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dialektika yang sedang terjadi.
Tanpa ketiganya kritik hanya akan kosong makna tak berisi atau lebih celaka lagi jika ia hanya berisi cacian, makian, fitnah tak berdasar, sentimen sara, hanya memuat dimensi pragmatis seputar status quo semata dan sederet perilaku non etis lain.