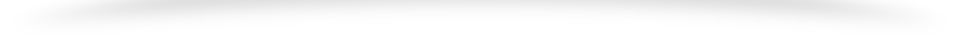PeciHitam.org – Hari Raya Idul Fitri merupakan saat-saat yang paling ditunggu bagi sebagian orang. Pasalnya Idul Fitri atau yang biasa disebut lebaran merupakan salah satu moment yang digunakan sebagai ajang silaturahmi bagi kaum muslimin di Indonesia.
Jika dilihat dari kata lebaran sendiri, berasal dari akar kata lebar yang artinya selesai. Maksudnya telah selesainya pelaksanaan Ibadah puasa Ramadhan dan memasuki bulan Syawal/Idul Fitri.
Demi menyambut tamu-tamu yang ingin bersilaturahmi, biasanya tuan rumah menyiapkan sajian berupa ketupat yang berbahan dasar beras yang direbus dengan dibungkus janur anyam berbentuk segi empat.
Entah nantinya disajikan dengan santan ayam ataupun yang lainnya. Namun biasanya ketupat inilah yang menjadi pokoknya.
Kebiasaan tersebut akhirnya melahirkan tradisi yang disebut dengan kupatan atau riyaya kupat. Konon tradisi ini telah ada dari zaman Walisongo, yang sejatinya merupakan produk dakwah para wali itu sendiri.
Daftar Pembahasan:
Pengertian Kupatan
Tradisi kupatan digelar seminggu setelah Idul Fitri, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Biasanya dikumpulkan di suatu tempat seperti masjid atau mushalla, seluruh warga membawa hidangan yang di dominasi dengan ketupat.
Hidangan yang terkumpul tersebut inilah nantinya digunakan untuk selamatan. Adapun perlengkapan upacaranya menggunakan ketan, kolak, apem yang diberi wadah pisang yang dibentuk sedemikian rupa yang disebut takir.
Makna Filosofis Tradisi Kupatan
Setiap bagian dalam tradisi tersebut memiliki makna filosofis di dalamnya. Menurut Zastrouw Al-Ngatawi, tradisi ini merupakan bentuk dari sublimasi dari ajaran Islam dalam tradisi masyarakat Nusantara.
Melalui tradisi inilah, walisongo mengenalkan ajaran Islam mengenai cara bersyukur kepada Allah SWT, bersedekah, dan saling menjalin silaturrahim.
Ketan sendiri merupakan perlambang yang diambil dari kata khatam (selesai) melakukan ibadah, takir dari kata dzikir, dan apem dari kata afwan yang berarti ampunan dari dosa.
Untuk nama kupat sendiri merupakan singkatan dari ngaku lepat (mengakui kesalahan) yang menjadi simbol untuk saling memaafkan.
Bungkus kupat yang terbuat dari janur (sejatine nur), ini melambangkan kondisi umat muslim setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan suci Ramadhan secara pribadi-pribadi mereka kembali kepada kesucian/jati diri manusia (fitrah insaniyah) yang bersih dari noda serta bebas dari dosa.
Isi kupat yang bahannya hanya berupa segenggam beras, namun karena butir-butir beras tadi sama menyatu dalam seluruh slongsong janur dan rela direbus sampai masak, maka jadilah sebuah makanan. Hal ini merupakan simbol persamaan dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Pesan moralnya agar kita sama-sama rela saling menjalin persatuan dan kesatuan dengan sesama muslim.
Laku Papat; Simbol Empat Sisi Kupat
Kupat juga diartikan sebagai “laku papat” yang menjadi simbol dari empat sisi dari ketupat. Laku papat yaitu empat tindakan yang terdiri dari lebaran, luberan, leburan, laburan. Maksud dari empat tindakan tersebut antara lain:
Pertama, Lebaran yaitu suatu tindakan yang berarti telah selesai yang diambil dari kata lebar, maksudnya selesai dalam menjalani ibadah puasa dan diperbolehkan untuk menikmati makanan.
Kedua, Luberan berarti meluber, melimpah ruah. Perumpamaan seseorang yang melakukan sedekah dengan ikhlas bagaikan air yang berlimpah meluber dari wadahnya.
Ketiga, Leburan berarti lebur atau habis. Idul Fitri biasanya dijadikan waktu yang pas untuk saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dosa-dosa juga diampuni, sehingga segala kesalahan yang telah dilakukan menjadi suci bagai anak yang baru lahir.
Keempat, Laburan berasal dari kata labur atau kapur yang berarti putih bersih. Masyarakat dahulu biasa mengecat rumahnya dengan dilabur atau menggunakan kapur berwarna putih.
Harapannya setelah dosa dan kesalahan telah dihapus, seseorang dapat selalu menjaga kebersihan hati yang suci. Manusia dituntut agar selalu menjaga perilaku dan jangan mengotori hati yang telah suci.
Begitu dalamnya makna yang terkandung di dalamnya. Mungkin kita sering mendengarnya dari para penceramah ataupun khatib saat lebaran yang senantiasa mengingatkan kita tentang substansi perayaan tersebut.
Sekaligus juga menunjukkan cara dakwah yang luar biasa bijak dari Walisongo, Islam ramah, bukan marah yang mampu merangkul tiap masyarakat agar terhubung erat dengan ajaran Islam melalui pendekatan budaya.
Apakah Tradisi Kupatan Bid’ah?
Idul Fitri (1 Syawal) merupakan momentum dimana semua orang Islam diharamkan berpuasa. Bagi fakir miskin, malam harinya sudah diberi zakat fitrah, harapannya tentu agar pada moment Idul Fitri tersebut tidak berpuasa karena tidak memiliki makanan di rumah.
Pada hari berikutnya orang Islam sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) untuk melakukan puasa selama enam hari atau biasa dikenal dengan nama puasa syawal, mulai dari tanggal dua Syawal, baik secara langsung dan berurutan, atau secara terpisah-pisah asalkan masih dalam bulan Syawwal. Hal ini sebagaimana sabda nabi SAW pada hadis dibawah ini:
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ. رواه مسلم – الجامع الصغير ص
Artinya :
“Barang siapa berpuasa Ramadlan kemudian mengikutinya dengan puasa enam hari di bulan syawwal, maka yang demikian itu seperti puasa setahun”. (HR. Imam Muslim)
Lalu Apakah Tradisi Kupatan Termasuk Bid’ah?
Perlu kami uraikan dahulu, ada dua macam bid’ah, yaitu bid’ah hasanah (baik) dan bid’ah sayyi’ah (buruk). Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul al-Ihtifal bidzikra Maulid an-Nabi menjelaskan:
قَالَ اْلإِمَامُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَحْدَثَ وَخَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ أَثَرًا فَهُوَ الْبِدْعَةُ الضَّالَّةُ، وَمَا أَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْمَحْمُوْدُ.
Artinya: “Imam Syafi’i berpendapat bahwa amalan apa saja yang baru diadakan dan amalan itu jelas menyimpang dari kitabullah, sunnah rasul, ijma’us shahabah atau atsaratut tabi’in, itulah yang dikategorikan bid’ah dlalalah/sesat atau tercela. Sedangkan amalan baik yang baru diadakan dan tidak menyimpang dari salah satu dari empat pedoman di atas, maka hal tersebut termasuk hal yang terpuji”.
Kemudian beliau menyimpulkan pendapat Imam Syafi’i tersebut sebagai berikut :
فَكُلُّ خَيْرٍ تَشْتَمِلُهُ اْلأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَمْ يُقْصَدْ بِإِحْدَاثِهِ مُخَالَفَةُ الشَّرِيْعَةِ وَلَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مُنْكَرٍ فَهُوَ مِنَ الدِّيْنِ.
Artinya : “Jadi setiap kebaikan yang tercakup dalam dalil-dalil syar’i dan mengadakannya tidak ada maksud menyimpang dari aturan syari’at serta tidak mengandung kemunkaran, maka hal itu termasuk “ad-din” (urusan agama)”.
Dalam hal ini, tradisi kupatan dikategorikan sebagai ibadah ghairu mahdlah (ritul tidak murni) yang perintahnya ada, tetapi teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, maka tradisi itu dianggap sebagai amrun mustahsan (sesuatu yang dianggap baik).
Tradisi tersebut memang belum ada di zaman nabi. Namun hal-hal yang terdapat di dalamnya sudah ada dan diperintahkan oleh nabi yang pelaksanaannya disatukan menjadi sebuah tradisi. Tentu hal ini justru dapat dikatakan bid’ah namun dalam artinya positif yakni inovasi.
Dengan demikian, menempatkan hukum tradisi kupatan dalam Islam harus dilihat dari substansi masalahnya, yakni ajaran silaturrahim, saling memaafkan dan pemberian shadaqah/sedekah yang mana hal tersebut perintahnya ada dalam dalil syar’i, sementara teknisnya bisa dilakukan dengan beragam cara.
Kurang tepat rasanya jika tradisi kupatan disebut sebagai bid’ah atau tambahan dalam beribadah. Sebab, tradisi kupatan adalah budaya lokal yang memiliki keterkaitan dengan syariat Islam. Maka dari itu kupatan tidak bisa dihukumi sebagai penyimpangan, apalagi tindakan sesat (dlalalah).
Wallahu A’lam.