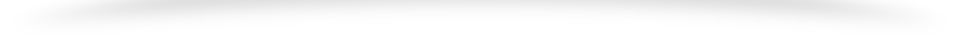PeciHitam.org – Sudah bukan rahasia lagi, bahwa netralitas dalam keilmuan adalah menjadi prinsip para pemikir. Meski pada dasarnya mereka sadar jika netralitas keilmuan terutama bidang agama adalah sesuatu yang naif.
Karena jika netralitas itu dianggap terdapat pada formulasi ilmu, maka ilmu sendiri pada dasarnya, adalah alat yang akan tunduk pada pilihan-pilihan subjektif para pengambil keputusan.
Artinya, jika netralitas ilmu bisa dipertahankan pada tataran ontologisnya di tangan ilmuwan yang bersangkutan, maka pada tataran aksiologisnya di tangan praktisi dan para pengambil keputusan, netralitas itu sepenuhnya sudah tidak lagi ada.
Dalam hal ini KH. Masdar Farid setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa prinsip netralitas yang sering dikedepankan oleh para ilmuwan, termasuk ilmuwan agama (fikih), pada hakikatnya merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab.
Ilmuwan seperti mereka ibarat seorang empu yang mendefinisikan tanggung jawabnya semata-mata hanya pada pembuat keris atau pedang dengan kemampuan tebas yang tinggi.
Sementara, dalam kenyataannya, keris dan pedang itu banyak digunakan orang untuk membunuh orang lain, sama sekali tidak mau tahu. Yang penting baginya adalah membuat keris dan pedang, setajam-tajamnya.
4 Watak Pemikiran Hukum, Kegelisahan Masdar Farid
Pertama, watak pemikiran hukum (fikih) yang juz’iyah, kasuistik dan micro-oriented. Akibat sangat kuatnya karakter ini, maka sudah tidak aneh lagi kalau kita mendengar pernyataan, bahwa fikih harus juz’iyyah, far’iyyah.
Di mana-mana pergumulan fikih selalu berawal dari kasus untuk kemudian dicarikan status hukumnya melalui ilhaq (qiyas) pada kasus lain yang telah ditentukan lebih dahulu status hukumnya, baik oleh Al-Quran atau Hadis Nabi.
Inilah proses pelacakan hukum yang paling standar yang telah diterima semua madzhab. Hanya, karena kesulitan yang dirasakan dalam menerapkan prosedur yang baku ini, kemudian ditawarkan modus penyangga seperti istihsan dari Imam Hanafi dan maslahah al-mursalah dari Imam Malik.
Hierarki hukum Islam yang ditawarkan Imam Syafi’i sepenuhnya mewakili logika pemikiran fikih yang disebut di atas. Baginya, nash-nash tentang hukum setelah Al-Quran tidak ada otoritas lain kecuali ijtihad, yang tak lain adalah “qiyas”: al-ijtihad huwa al-qiyas (ijtihad itu tidak lain adalah ber-qiyas).
Dan, Imam Ahmad mewarisi semangat ortodoksi dari Imam Syafi’i. Bahkan, dalam kadar yang jauh lebih tinggi, ia berpendirian bahwa, “secara teoritik, qiyas memang merupakan prosedur pemikiran Islam yang bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, secara historik, tidak benar-benar diperlukan.”
Seperti diketahui, berbeda dengan ketiga Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad hidup pada zaman yang mana hampir semua kebutuhan akan nash (hadis), yang diperlukan, oleh ahli hukum pada zamannya, telah tersedia. Di samping itu, pada dasarnya, tokoh terakhir ini, memang lebih merupakan pemerhati Hadis ketimbang pemikir hukum.
Kedua, watak pemikiran hukum yang kasuistik, hanya berguna untuk menangani persoalan secara pasca kejadian. Ia menjadi semisal tukang ketok yang porsinya adalah meluruskan kebengkokan-kebengkokan kecil sejauh dimungkinkan.
Artinya, jika kebengkokan kebengkokan itu telah sedemikian parahnya, dan ia sendiri merasa tidak bisa meluruskannya, maka yang terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut ini:
- dengan sikap fundamentalistiknya, ia terus saja dan menyatakan penolakannya terhadap kebengkokan itu, meskipun ia sadar bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa; atau
- dengan sikap realismenya, ia bersedia menerima, menjustifikasi dan berdamai dengan kebengkokan yang ada.
Ketiga, watak pemikiran hukum yang berorientasi pada penanganan kasus-perkasus, akan cenderung mengabaikan penanganan masalah-masalah strategis justru karena sifatnya yang memerlukan pendekatan sistematis.
Tidak ada salahnya, pemikiran hukum Islam memberikan perhatian pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mikro (juz’iyah). Tetapi, salah besar apabila perhatiannya terhadap hal-hal mikro tersebut membuatnya lupa menangani hal-hal yang bersifat makro.
Keempat, watak pemikiran hukum Islam (fikih) yang berangkat dari concern untuk mendeduksi ayat (hukum) adalah formalistiknya. Logika hukum seperti ini tidak akan pernah bertanya untuk apa suatu hukum ditetapkan, dan buat kepentingan siapa.
Yang penting baginya adalah bahwa suatu pemikiran hukum, dalam kasus apa pun, bisa dipertanggung jawabkan secara formal pada bunyi teks (nash) tertentu. Tak soal, apakah hukum itu dalam kenyataan historisnya telah menyentuh kemaslahatan orang banyak atau hanya menyan tuni kepentingan sekelompok orang saja.
Atau bahkan, ketika pemikiran hukum itu sudah tidak berhubungan dengan kepen dengan siapa pun. Asal secara formal terdapat teks yang bisa dijadikan rujukan, maka suatu pemikiran hukum, dalam tradisi fikih kita sampai sekarang, telah dianggap sah.
Tidak mengherankan apabila wajah fikih kita selama ini menjadi tampak begitu dingin, suatu wajah fikih yang secara keselu ruhan kurang menunjukkan pemihakan (engagement) terhadap, kepentingan masyarakat manusia.
Dalam terma keilmuan, sikap fikih seperti ini, adalah sikap netral -dengan dalih objektivitas keilmuan-tidak mau ditarik-tarik oleh kepentingan subjektif satu kelompok masyarakat tertentu. Bedanya, objektivitas keilmuan sekuler, patokannya pada data empirik, sementara objektivitas keilmuan agama (fikih) patokannya pada teks-teks normatif.
Ash-Shawabu Minallah