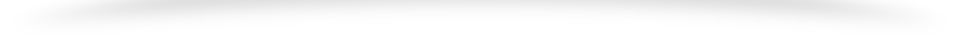Pecihitam.org – Penghujung tahun 2019 publik digemparkan oleh terbitnya buku “Menjerat Gus Dur”. Buku itu seakan menjadi bukti omongan Gus Dur pribadi bahwa “Biarlah sejarah yang akan menjawabnya” tentang apa dan bagaimana Presiden ke-4 itu dicongkel dari Istana Negara secara politis inkonstitusional.
Buku karya jurnalis Narasi TV Virdika Rizky Utama itu membeber siapa dalang dan aktor di balik pelengseran paksa Presiden Gus Dur. Kegemparan itu berasa sekali terutama di kalangan Nahdliyin dan para pecinta Gus Dur.
Berupaya melampaui viralitas buku itu sembari berusaha meredam emosi, saya sebagai pengagum Gus Dur, daripada terkungkung romantisme sejarah, saya memilih kembali berenang dan menyelami samudera intelektual Gus Dur. Risalah sederhana ini adalah wujud upaya itu.
Boleh dikata ini adalah metoda saya mendaras ide-ide Gus Dur tentang berbagai hal-ihwal. Membaca dan memahami apa yang dipikirkan dan diutulis Gus Dur serta sekaligus menuliskannya kembali dengan konstruk dan gaya bahasa saya pribadi.
Lantas bagaimana pendapat Gus Dur tentang sistem Islami? Dalam artikel berjudul “Adakah Sistem Islami?”, Gus Dur memulai teksnya dengan dua kutub penafsiran atas QS al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi “udkhulu fi al-silmi kaffah”. “Di sinilah letak perbedaan pendapat sangat fundamental di antara kaum muslimin,” tegas Gus Dur.
Dua kutub penafsir itu saya istilahkan dengan “muslim formal” dan “muslim kultural”. Muslim formal adalah kaum muslimin yang meyakini dan memperjuangkan formalisasi syariat Islam hingga tataran kebijakan publik bahkan pendirian negara Islam, dan ini mengandaikan adanya tafsir tunggal atas Islam dimana negara adalah subjeknya.
Muslim kultural adalah kaum muslimin yang meyakini Islam sebagai agama tidak perlu diformalisasikan sehingga keberislaman seseorang lebih bersifat atas kesadaran diri dan bebas dari paksaan institusi formal (negara).
Menurut Gus Dur, bagi muslim formal terjemah kata “al-silmi” dalam teks quranik di atas adalah Islam, sedang bagi muslim kultural makna “al-silmi” itu adalah kata sifat yang berarti kedamaian. Perbedaan alih bahasa ini pun memiliki dampak fundamental.
Mereka yang terbiasa dengan formalisasi (muslim formal), menurut cucu Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari itu, menafsirkan petikan ayat di atas sebagai landasan teologis akan keharusan mendirikan sebuah sistem pemerintahan yang berasas Islam. Karena itu, tambahnya, dapat dimengerti mengapa ada yang menganggap penting perwujudan “partai politik Islam” dalam kehidupan berpolitik.
Yang menarik, dan ini konsisten, dari Gus Dur adalah sikap kelegawaan pikirannya menerima yang liyan. Kendatipun artikel “Adakah Sistem Islami?” berintikan pemikiran Gus Dur menolak adanya formalisasi Islam dan atau negara Islam, ia masih sempat-sempatnya menyisihkan ruang dalam tubuh teks itu bagi aktualisasi inklusivitas sikapnya.
Hal ini tersirat dalam kalimatnya: “Tentu saja, demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati eksistensi parpol-parpol Islam, tetapi ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka”.
Gus Dur menolak ide formalisasi Islam sebab ide itu mengandaikan terbentuknya struktur hirarki di tengah-tengah rakyat (warga negara). Padahal, dalam sistem politik demokratis segenap warga negara adalah setara di mata hukum, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Gus Dur menulis: “Dalam kerangka kenegaraan sebuah bangsa, sebuah sistem Islami otomatis membuat warga negara non-muslim berada di bawah kedudukan warga negara beragama Islam, alias menjadi warga negara kelas dua”.
Jelas bahwa selain problem penafsiran teks quranik, gagasan Gus Dur tentang tidak perlunya sebuah sistem Islami berdasar pada jiwa kebangsaan Gus Dur dimana menurutnya sistem Islami berdampak terbentuknya hirearki sosial warga negara kelas satu (muslim) dengan warga negara kelas dua (non-muslim).
Teranglah bahwa semangat egalitariansime dan emansipasi Gus Dur tercermin di sini. Bahwa ketika sebuah bangsa telah mengukuhkan dirinya dalam semangat persatuan, sebagaimana tercermin dalam lanskap sejarah dan pada butir ketiga Pancasila, sekat-sekat primordial dan sektarian sudah sepatutnya dileburkan dalam satu ikatan kesetaraan.
Selaian dua argumen di atas, alasan mengapa Gus Dur tidak mendukung formalisasi syariat Islam adalah sebab, menurutnya, untuk menjadi muslim yang taat tidak memerlukan sebuah sistem formal yang Islami.
Hal ini ditegaskan olehnya dengan merangkum sebuah isi kandungan ayat quran bahwa untuk menjadi “muslim yang baik” seseorang harus menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar.
“Dengan demikian, mewujudkan sebuah sistem Islami tidak termasuk syarat bagi seseorang untuk dianggap muslim yang taat,” tegas Gus Dur. Gagasan Gus Dur dalam “Adakah Sistem Islami?” penting untuk kita, setidaknya saya pribadi, baca kembali.
Sebab, gagasan akan kewajiban mendirikan negara Islam dan atau khilafah Islamiyah masih terus menjadi wacana liar di khalayak publik. Dengan kembali “ngaji” kepada Gus Dur, minimalnya kita bisa memahami dan menjawab tanya “mengapa Gus Dur dicintai nyaris semua rakyat Indonesia tanpa memandang apa agamanya?”
Wallahul muwaffiq.