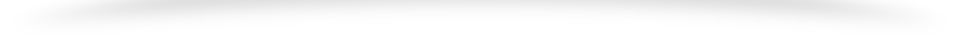Pecihitam.org – Hadits Shahih Al-Bukhari No. 609-611 – Kitab Adzan ini, Imam Bukhari memulai hadis ini dengan judul “Kewajiban Shalat Jamaah”. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan shalat berjamaah. Keterangan hadist dikutip dan diterjemahkan dari Kitab Fathul Bari Jilid 4 Kitab Adzan. Halaman 153-172.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi’] dari [‘Abdullah bin ‘Umar], bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Shalat berjama’ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.”
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] telah menceritakan kepadaku [Ibnu Al Had] dari [‘Abdullah bin Khabbab] dari [Abu Sa’id Al Khudri], bahwa dia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Shalat berjama’ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat.”
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ
Terjemahan: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma’il] berkata, telah menceritakan kepada kami [‘Abdul Wahid] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al A’masy] berkata, aku mendengar [Abu Shalih] berkata, Aku mendengar [Abu Hurairah] berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Shalat seorang laki-laki dengan berjama’ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama’ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo’akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, ‘Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia’. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti pelaksanaan shalat.”
Keterangan Hadis: Menurut Ibnu Al Manayyar bahwa makna lahiriah judul bab ini (keutamaan shalat berjamaah) bertentangan dengan judul bab sebelumnya. Kemudian dia menjelaskannya secara panjang lebar, tapi dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kewajiban tidak berarti tidak memiliki keutamaan, tetapi keutamaan itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, maka yang dimaksud hadits tersebut adalah penjelasan tentang tambahan pahala bagi shalat jamaah dibanding shalat sendirian.
صَلَاة الْجَمَاعَة تَفْضُل صَلَاة الْفَذّ (shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian). Kata al fadzdz الْفَذّ berarti menyendiri. Dikatakan, “fadzdza rajulun min ashhaabihi (seseorang menyendiri dari teman-temannya)”, yakni apabila ia tinggal seorang diri tanpa ada sahabat yang menemaninya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi dengan penyajian yang lebih jelas, صَلَاة الرَّجُل فِي الْجَمَاعَة تَزِيد عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ (Shalat seseorang berjamaah melebihi daripada shalatnya seorang diri).
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (dengan terpaut dua puluh tujuh derajat) At Tirmidzi berkata, “Kebanyakan perawi yang menukil hadits ini dari Abu Hurairah mengatakan, ‘Dua puluh lima derajat’ kecuali Ibnu Umar, dimana ia mengatakan, ‘Dua puluh tujuh derajat’.”
Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan riwayat dari beliau mengenai hal itu kecuali riwayat yang dikutip oleh Abdurrazzaq, dari Abdullah Al Umari, dari Nafi’, dimana dia berkata, “Dua puluh lima derajat.” Akan tetapi Al Umari adalah seorang perawi yang lemah. Kemudian tercantum dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab Mustakhraj-nya melalui jalur Abu Usamah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi, dimana dia berkata, “Dua puluh lima derajat.” Akan tetapi riwayat ini dianggap syadz (ganjil) karena menyelisihi riwayat yang dinukil oleh para pakar di antara murid-murid Ubaidillah serta murid-murid Nafi’, meskipun Abu Usamah adalah seorang perawi yang tsiqah (terpercaya) pula.
Adapun riwayat yang tercantum dalam Shahih Muslim melalui riwayat Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi’ menyebutkan dengan lafazh, بِضْعٍ وَعِشْرِينَ (dua puluh lebih), tidak berbeda dengan riwayat para huffazh (pakar hadits), karena kata بِضْعٍ bisa saja berarti tujuh. Sedangkan selain Ibnu Umar telah dinukil melalui jalur shahih dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah seperti di bab ini, dari Ibnu Mas’ud yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, dari Ubay bin Ka’ab yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Al Hakim, serta dari Aisyah dan Anas yang dikutip oleh As-Sarraj. Diriwayatkan pula melalui beberapa jalur periwayatan lemah dari Mu’adz, Shuhaib, Abdullah bin Zaid dan Zaid bin Tsabit, semuanya dikutip oleh Ath-Thabrani. Semuanya menyebutkan “dua puluh lima derajat” kecuali riwayat Ubay yang mengatakan, “dua puluh empat atau dua puluh lima derajat”, yakni disertai unsur keraguan.
Selain riwayat Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad dikatakan, “Dua puluh tujuh derajat”, namun pada sanadnya terdapat Syarik Al Qadhi yang lemah hafalannya. Kemudian dalam riwayat Abu Awanah disebutkan dengan lafazh بِضْعٍ وَعِشْرِينَ (dua puluh lebih), namun ini tidak berbeda dengan riwayat lainnya karena kata al bidh’u bisa saja bermakna lima. Dengan demikian semua riwayat kembali kepada “dua puluh tujuh dan dua puluh lima”, karenanya tidak ada pengaruh bagi keraguan yang ada. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana di antara keduanya yang lebih akurat. Sebagian mengatakan yang lebih akurat adalah riwayat yang menyatakan dua puluh lima, karena para perawinya lebih banyak. Namun ada pula yang mengatakan dua puluh tujuh, karena terdapat tambahan dari perawi ‘adil’ (tidak fasik) serta ‘hafizh’ (pakar hadits).
Demikian pula terdapat perbedaan di tempat lain dari hadits ini, yaitu tentang kata penghitung dari bilangan yang ada. Pada semua riwayat diungkapkan dengan kata دَرَجَةً (derajat) atau tanpa menyebutkannya. Berbeda dengan jalur-jalur periwayatan dari Abu Hurairah, dimana pada sebagiannya diungkapkan dengan kata ضِعْفًا (lipat) pada sebagiannya dengan kata جُزْءًا (bagian) dan pada sebagiannya dengan kata دَرَجَةً (derajat), sedangkan pada sebagian lainnya dengan kata صَلَاةً (shalat). Adapun yang terakhir ini tercantum pula pada sebagian jalur periwayatan hadits Anas. Secara lahiriah bahwa yang demikian itu berasal dari para perawi, dan ada pula kemungkinan hal itu merupakan gaya bahasa dalam mengungkapkannya.
Adapun perkataan Ibnu Atsir, “Hanya saja dikatakan دَرَجَةً (derajat) dan bukan جُزْءًا, نَصِيبًا, حَظًّا atau yang sepertinya, karena yang dimaksud adalah pahala yang dating dari atas. Demikian pula halnya dengan derajat, dimana derajat (tingkatan) itu menuju ke arah atas.” Seakan-akan beliau mengatakan hal ini atas dasar bahwa lafazh dasarnya adalah “derajat”, sedangkan yang lainnya hanyalah perubahan dari para perawi. Akan tetapi perkataan beliau yang menafikan kata جُزْءًا tidak tepat, karena lafazh ini terbukti dinukil melalui riwayat yang akurat. Demikian pula hanya dengan kata ضِعْفًا (lipat).
Para ulama berusaha mengompromikan antara riwayat yang menyebutkan “dua puluh lima” dan “dua puluh tujuh” dengan beberapa cara:
Pertama, sesungguhnya menyebutkan angka yang kecil tidaklah menafikan angka yang besar. Pendapat ini merupakan perkataan mereka yang tidak berpedoman dengan “majhum al ‘adad”.[1] Akan tetapi pendapat ini telah dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Syafi ‘i, dan dikatakan bahwa ini termasuk pernyataan tekstual dari sang imam. Atas dasar ini dikatakan:
Kedua, kemungkinan beliau SAW diberitahu tentang dua puluh lima, kemudian Allah SWT memberitahukan tambahan keutamaan, yaitu dua puluh tujuh. Akan tetapi hal ini membutuhkan penelitian sejarah, mana di antara kedua riwayat itu yang lebih dahulu. Di samping itu, bolehnya nasakh dalam keutamaan merupakan masalah yang diperselisihkan. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa riwayat yang menyebutkan “dua puluh lima” lebih dahulu daripada riwayat yang menyebutkan “dua puluh tujuh”, tapi kita masih dapat mengatakan bahwa keutamaan-keutamaan yang berasal dari Allah SWT bisa saja bertambah tapi tidak bisa berkurang.
Ketiga, sesungguhnya perbedaan kedua angka itu disebabkan perbedaan kata penghitungnya. Atas dasar ini maka dikatakan; sesungguhnya kata دَرَجَةً (derajat) lebih kecil daripada kata جُزْءًا (bagian). Namun pandangan ini dikritik, karena perawi yang menukil kata دَرَجَةً menukil pula kata جُزْءًا Sebagian mereka mengatakan, “Kata جُزْءًا (bagian) berlaku di dunia, sedangkan kata دَرَجَةً (derajat) berlaku di akhirat.” Pandangan ini juga berdasarkan perbedaan kedua kata tersebut.
Keempat, perbedaan tersebut berdasarkan jauh dekatnya seseorang dari masjid.
Kelima, perbedaan tersebut tergantung kondisi orang yang shalat, seperti lebih berilmu atau lebih khusyuk.
Keenam, perbedaan juga karena tempat pelaksanaan shalat, yakni shalat yang dilakukan di masjid berbeda dengan di tempat lainnya.
Ketujuh, perbedaan juga dikarenakan menunggu shalat atau tidak.
Kedelapan, perbedaan tersebut juga berdasarkan apakah ia mendapatkan seluruh shalat atau hanya sebagiannya.
Kesembilan, perbedaan juga tergantung banyak sedikitnya jamaah yang hadir.
Kesepuluh, “dua puluh tujuh” derajat khusus untuk shalat fajar (Subuh) sedangkan “dua puluh lima” derajat khusus untuk shalat Isya. Ada pula yang mengatakan “dua puluh tujuh” derajat khusus untuk shalat Subuh dan Ashar, sedangkan “dua puluh lima” derajat bagi shalat-shalat lainnya.
Kesebelas, “dua puluh tujuh” khusus untuk shalat-shalat jahriyah (yakni shalat yang dikeraskan bacaannya) sedangkan “dua puluh lima” khusus untuk shalat-shalat sirriyah (shalat yang tidak dikeraskan bacaannya). Pandangan ini menurutku lebih tepat berdasarkan alasan yang akan saya sebutkan.
Sesungguhnya hikmah penyebutan angka tersebut secara khusus tidak dapat diketahui maknanya. Ath-Thaibi menukil dari At-Turbisyti yang kesimpulannya, “Sesungguhnya yang demikian itu tidak dapat diketahui berdasarkan pendapat, bahkan penjelasannya harus dikembalikan kepada ilmu kenabian, dan ilmu para cendekiawan pun tidak mampu menganalisanya secara keseluruhan.” Dia mengatakan, “Mungkin faidahnya adalah mengumpulkan kaum muslimin dalam satu barisan seperti barisan para malaikat, mengikuti imam (pemimpin), menampakkan syiar Islam dan lain sebagainya.” Seakan-akan dia mengisyaratkan penjelasan yang telah saya sebutkan dari selainnya. Sedangkan mereka yang mengklaim bahwa apa yang disebutkannya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan, sungguh tidak memahami apa yang dimaksud olehnya.
Al Karmani mensinyalir kemungkinan lain, yakni sesungguhnya yang menjadi dasar adalah shalat fardhu yang berjumlah lima waktu. Lalu jumlah tersebut hendak diperbanyak, maka dikalikan dengan jumlah yang sama sehingga hasilnya adalah dua puluh lima. Al Karmani menyebutkan kesesuaian lain bagi angka dua puluh tujuh dari sisi bahwa jumlah rakaat shalat fardhu beserta shalat-shalat sunah yang menyertainya (sunah rawatib) semuanya adalah dua puluh tujuh rakaat. Adapun ulama lainnya mengatakan, “Sesungguhnya kebaikan shalat adalah sepuluh. Apabila digabungkan dengan orang lain, maka jumlahnya menjadi dua puluh. Kemudian jumlah ini di tarn bah dengan jumlah shalat lima waktu, maka hasilnya adalah dua puluh lima. Atau ditambahkan jumlah hari dalam sepekan (sehingga semuanya berjumlah dua puluh tujuh).” Tapi cukup jelas bagaimana rusaknya pandangan ini. Sebagian mengatakan bahwa bilangan terdiri dari puluhan, ratusan dan ribuan. Sebaik-baik persoalan adalah yang pertengahan. Dengan demikian yang dijadikan patokan adalah bilangan ratusan, sementara angka yang tertera pada hadits adalah seperempat dari bilangan tersebut. Perkataan ini lebih fatal dari yang sebelumnya.
Saya membaca manuskrip (tulisan tangan) Syaikh Al Balqini yang beliau cantumkan dalam kitab Al Umdah, “Sehubungan dengan kedua angka ini, saya melihat pandangan yang belum pernah dikemukakan; karena lafazh Ibnu Umar ‘Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendiri’ maksudnya adalah shalat berjamaah seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ‘Shalat seseorang dalam jamaah. Berdasarkan hal ini, maka setiap salah seorang di antara mereka shalat dalam jamaah. Minimal jumlah suatu jamaah adalah tiga orang, hingga tiap-tiap salah seorang di antara mereka shalat dalam jamaah dan masing-masing mendatangkan satu kebaikan. Lalu satu kebaikan ini dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, maka jumlah kebaikan semuanya adalah tiga puluh. Namun pada hadits hanya menyebut keutamaan tambahan yakni dua puluh tujuh tanpa menyebut angka pokok, yakni tiga.”
Kemudian tampak bagi saya pandangan yang berusaha mengompromikan kedua angka yang tercantum dalam hadits, yaitu bahwasanya jumlah minimal sesuatu jamaah adalah seorang imam dan seorang makmum. Kalau bukan karena imam niscaya makmum tidaklah dinamakan sebagai makmum, demikian pula sebaliknya. Apabila Allah SWT telah menganugerahkan kepada orang yang shalat berjamaah tambahan pahala hingga dua puluh lima derajat, maka lafazh hadits yang menyebut angka “dua puluh lima” dipahami bahwa yang dimaksud hanyalah keutamaan tambahan. Sementara lafazh hadits yang menyebut angka “dua puluh tujuh,” dipahami bahwa yang dimaksud adalah keutamaan yang pokok beserta keutamaan tambahan.
Sebagian ulama membahas pula faktor-faktor yang menyebabkan adanya derajat-derajat tersebut, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa, demikian pernyataan Ibnu Al Jauzi. Sementara Al Muhib Ath-Thabari berkata, “Sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam hadits Abu Hurairah -yakni hadits ketiga di bah ini- terdapat isyarat sebagian faktor-faktor tersebut. Lalu ditambahkan hal-hal lain yang juga disebutkan berkenaan dengan masalah itu.” Ibnu Baththal telah merinci semuanya, dimana perinciannya diikuti oleh sejumlah pensyarah Shahih Bukhari. Akan tetapi Az-Zain bin Al Manayyar mengkritik sebagian apa yang dikatakan Ibnu Baththal, lalu dia mengemukakan perincian lain. Saya meneliti kembali apa yang berhubungan dengan masalah itu seraya menghapus faktor-faktor yang tidak hanya terdapat pada shalat berjamaah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya derajat-derajat tersebut adalah:
1. Menjawab muadzdzin disertai niat untuk shalat berjamaah.
2. Bersegera untuk shalat di awal waktu.
3. Berjalan menuju masjid dengan tenang.
4. Masuk masjid sambil berdoa. ·
5. Shalat Tahiyatul masjid ketika memasukinya dan berniat shalat jamaah.
6. Menunggu pelaksanaan shalat jamaah.
7. Shalawat dan permohonan ampunan oleh malaikat untuk orang yang shalat berjamaah.
8. Persaksian para malaikat atas mereka.
9. Menjawab qamat.
10. Selamat dari gangguan syetan ketika syetan itu lari saat qamat.
11. Berdiri menunggu takbiratul ihram imam atau masuk bersamanya pada posisi dimana ia mendapati imam.
12. Mendapati tabiratul ihram imam.
13. Meratakan shaf serta mengisi celah-celahnya.
14. Menjawab imam saat ia mengucapkan “sami’allahu Ziman hamidah”.
15. Umumnya terdapat perasaan aman dari lupa serta mengingatkan imam apabila lupa dengan mengucapkan tasbih (سبحان الله ), atau membenarkan bacaannya yang keliru.
16. Adanya rasa khusyuk serta terpelihara dari hal-hal yang melalaikan.
17. Memperbaiki penampilan.
18. Diliputi oleh para malaikat.
19. Latihan belajar bacaan yang baik serta mengetahui rukun-rukunnya.
20. Menampakkan syiar Islam.
21. Mengecewakan syetan dengan berkumpul dalam rangka ibadah serta tolong-menolong dalam ketaatan dan membangkitkan semangat mereka yang bermalas-malasan.
22. Selamat dari sifat munafik serta gangguan orang lain karena diduga tidak pernah melakukan shalat.
23. Menjawab salam imam.
24. Mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dalam berdoa dan berdzikir, serta yang sempurna dapat mengisi yang kurang.
25. Menyatukan hati sesama tetangga demi terciptanya perjanjian di antara mereka pada waktu-waktu shalat.
Inilah dua puluh lima perkara yang masing-masing diperintahkan atau dianjurkan secara khusus. Masih ada dua hal lagi yang khusus terdapat pada shalat-shalat jahriyah; yakni berdiam saat membaca seraya mendengarkannya, dan mengucapkan “amin” saat imam mengucapkan “amin” agar bersamaan dengan ucapan “amin” para malaikat. Dari sinilah maka dapat dikatakan bahwa dua puluh tujuh derajat khusus bagi shalat-shalat jahriyah,[2] wallahu a’lam.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan: Pertama, konsekuensi dari faktor-faktor yang saya sebutkan bahwa pahala yang berlipat ganda tersebut diperoleh apabila shalat jamaah dilaksanakan di masjid. Inilah pendapat yang lebih tepat menurut pandangan saya, sebagaimana akan diterangkan lebih mendalam pada pembahasan selanjutnya.
Apabila dikatakan bahwa pelipatgandaan tersebut tidak khusus pada shalat jamaah di masjid, maka sesungguhnya yang hilang di antara faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi ada tiga; yaitu berjalan menuju masjid, masuk masjid serta shalat Tahiyatul masjid. Namun ketiga hal ini mungkin diganti dengan cara memisahkan dua faktor yang pada penjelasan di atas hanya dijadikan satu faktor saja, seperti dua faktor paling akhir, karena sesungguhnya manfaat berkumpul dalam rangka berdoa dan dzikir berbeda dengan manfaat saling mengisi antara yang memiliki berkah sempurna dengan orang yang memiliki kekurangan.
Demikian juga faidah menyatukan hati di antara tetangga, berbeda dengan faidah terciptanya perjanjian di antara mereka. Faidah rasa aman para makmum dari lupa berbeda dengan faidah mengingatkan imam apabila lupa. Ketiga hal ini dapat menggantikan tiga perkara yang hilang tadi, sehingga maksud yang saya ketengahkan di atas tetap tercapai.
Kedua, pernyataan yang saya kemukakan di atas tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa sebagian faktor-faktor tersebut hanya didapatkan oleh sebagian orang yang shalat berjamaah dan tidak didapatkan oleh sebagian yang lain. Seperti bersegera datang pada awal waktu, menunggu jamaah, menunggu takbiratul ihram imam, dan yang sepertinya. Sebab saya katakan bahwa semua itu didapatkan oleh orang yang hendak melakukan shalat jamaah, asalkan ia telah berniat meski tidak sempat melakukannya, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.
Ketiga, makna “derajat” atau “bagian”, adalah semua orang yang shalat berjamaah memperoleh pahala shalat sendirian, dan dilipatgandakan sebanyak jumlah yang tersebut dalam hadits, Sementara Ibnu Daqiq Al Id mensinyalir bahwa sebagian ulama mengemukakan pandangan yang lain. Dia berkata, “Akan tetapi pandangan pertama lebih tepat, karena hal itu telah disebutkan dengan jelas pada sebagian riwayat.” Demikian pernyataan Ibnu Daqiq Al Id.
Sepertinya dia mengisyaratkan pada riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim yang pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan lafazh, (Shalat jamaah sebanding dengan dua puluh lima (derajat) daripada shalat sendirian).
بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ (dengan dua puluh lima) Dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan lafazh, خَمْسًا وَعِشْرِينَ Lalu Ibnu Hibban dan Abu Daud memberi tambahan pada riwayat mereka melalui jalur lain dari Abu Sa’id, فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاة فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً (Apabila ia melakukan shalat itu di tempat jauh dari pemukiman seraya ia menyempurnakan ruku’ dan sujud, niscaya mencapai lima puluh shalat). Seakan-akan rahasia yang terkandung adalah bahwa shalat jamaah tidak terlalu ditekankan bagi seorang musafir, karena kondisi yang sulit. Bahkan Imam An-Nawawi telah menukil pernyataan yang mengatakan tidak adanya perbedaan pendapat tentang tidak wajibnya shalat jamaab saat safar.[3] Tetapi pernyataannya ini perlu dikoreksi, karena sesungguhnya ia menyalahi pernyataan tekstual dari Imam Syafi’i. Abu Daud meriwayatkan dari Abdul Wahid, dia berkata, “Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa shalat seseorang di tempat yang jauh dari pemukiman melebihi shalat yang ia lakukan dengan berjamaah.” Seakan beliau menyimpulkan hal ini dari lafazh hadits, “Apabila ia melakukannya”, yang mana menurutnya mencakup shalat jamaah dan shalat sendirian. Akan tetapi memahami bahwa yang dimaksud adalah shalat fardhu akan lebih tepat. Inilah makna yang tampak dari konteks hadits.
Menjadi konsekuensi pernyataan Imam An-Nawawi, bahwa pahala amalan sunah melebihi pahala amalan wajib bagi mereka yang mewajibkan shalat berjamaah. Sementara Al Qarafi mempertanyakan dasar hadits itu sendiri.[4] Pertanyaan ini lahir dari pandangan beliau, bahwa shalat jamaah hukumnya sunah. Kemudian beliau menjawab permasalahan itu dengan mengatakan, “Sesungguhnya pahala yang disebutkan dalam hadits merupakan pahala shalat fardhu itu sendiri yang dilaksanakan dengan berjamaah, maka tidak berarti pahala amalan sunah melebihi pahala amalan wajib.” Tapi jawaban ini kembali beliau tanggapi dengan mengemukakan kasus apabila seseorang shalat sendirian kemudian mengulangi shalatnya dengan berjamaah. Maka di sini pahala shalat fardhu ia dapatkan dari shalat yang dilaksanakan sendirian, sedangkan penggandaan pahala ia dapatkan dari shalat yang ia lakukan berjamaah. Dengan demikian persoalan belum terpecahkan dan tetap sebagaimana adanya. Namun apa yang ia katakan perlu diluruskan, sebab penggandaan pahala tersebut didapatkan bukan karena orang itu mengulangi shalatnya, bahkan hal itu ia peroleh karena melakukan shalat berjamaah. Karena apabila ia mengulangi shalatnya sendirian, maka ia hanya mendapatkan pahala satu kali shalat. Dengan demikian, pernyataan beliau tidak berkonsekuensi bahwa pahala amalan sunah lebih utama dari pahala amalan wajib.
Keterangan lain yang menyebutkan jumlah yang melebihi jumlah yang disebutkan pada hadits di atas, adalah riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, (Kelebihan shalat berjamaah atas shalat sendirian adalah dua puluh lima derajat. Dia berkata, “Apabila jumlah yang shalat lebih banyak dari dua puluh lima orang, maka kelebihan tersebut sama seperti jumlah orang yang ada di dalam masjid.” Seorang laki-laki berkata, “Meskipun jumlah mereka sepuluh ribu?” dia menjawab, “Ya.”)
Pada dasarnya riwayat ini memiliki hukum marfu‘ (langsung dari Nabi SAW), karena yang demikian tidak mungkin didasarkan pada pemikiran semata. Hanya saja riwayat ini tidak akurat.
فِي بَيْته وَفِي سُوقه (di rumahnya dan di pasarnya). Hal itu menunjukkan bahwa shalat di masjid dengan berjamaah melebihi shalat di rumah dan di pasar, baik berjamaah atau sendirian, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Dia berkata, “Adapun yang nampak dari hadits tersebut bahwa shalat jamaah di masjid berbeda dengan shalat sendirian selain di masjid. Hanya saja hadits tersebut berbicara dalam konteks yang umum, dimana apabila seseorang tidak hadir shalat berjamaah di masjid, maka umumnya ia melakukan shalat sendirian.” Dia melanjutkan, “Berdasarkan keterangan ini, maka terjawablah permasalahan yang dikemukakan oleh sebagian orang yang menyamakan shalat di rumah dan di pasar.”
Namun apabila hadits itu dipahami sebagaimana makna labiriahnya, maka tidak ada kemestian terjadi persamaan antara shalat di rumah dan shalat di pasar. Karena bukan menjadi ketentuan jika keduanya sama-sama lebih rendah dibandingkan shalat berjamaah di masjid, maka salah satunya tidak lebih utama daripada yang lainnya. Demikian pula tidak ada ketentuan bahwa shalat berjamaah di rumah atau di pasar tidak lebih utama dibanding shalat sendirian pada keduanya. Bahkan, tampaknya pelipatgandaan (pahala) yang disebut dalam hadits khusus untuk shalat jamaah di masjid. Sedangkan shalat di rumah lebih utama daripada shalat di pasar berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa pasar merupakan tempat syetan. Lalu shalat berjamaah di rumah dan di pasar lebih utama daripada shalat sendirian di rumah dan di pasar.
Telab dinukil pendapat dari sebagian sahabat yang menyatakan bahwa dilipatgandakannya pahala hingga dua puluh lima kali lipat khusus didapatkan apabila orang yang berjamaah cukup banyak dan dilakukan di masjid-masjid umum, meski diakui adanya keutamaan pada selain itu. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad hasan dari Aus Al Mu’afiri bahwasanya ia berkata kepada Abdullah bin Amr bin Ash, “Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berwudhu lalu memperbaiki wudhunya kemudian shalat di rumahnya?” Dia menjawab, “Baik dan bagus.” Aus berkata, “Bagaimana jika ia shalat di masjid keluarganya?” Dia menjawab, “Baginya lima belas kali shalat.” Aus berkata, “Bagaimana jika ia berjalan ke masjid jami’ lalu shalat di sana?” Dia berkata, “Baginya dua puluh lima.”
Humaid bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab At-Targhib sama seperti hadits Watsilah. Lalu ia mengkhususkan pahala dua puluh lima tersebut di masjid Kabilah. Dia berkata, “Adapun shalat yang dilakukan di masjid jami’ -yakni masjid yang digunakan untuk shalat Jum’at- nilainya sama dengan lima ratus kali shalat.” Tapi sanad riwayat ini lemah.
وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ (dan yang demikian itu bahwasanya apabila ia berwudhu) Secara lahiriah hal-hal yang disebutkan dalam kalimat ini dan seterusnya merupakan sebab dilipatgandakannya pahala tersebut. Seolah-olah dikatakan, “Sebab pelipatgandaan pahala tersebut adalah ini dan itu.” Jika demikian, maka pahala tersebut tidak didapatkan melainkan dengan melakukan semua sebab yang disebutkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sebab tersebut tidak menjadi tujuan utama
Makna keterangan tambahan yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah sangat masuk akal, maka berpegang dengannya cukup beralasan. Sedangkan riwayat-riwayat yang tidak mencantumkan keterangan tambahan tidak bertentangan dengan riwayat Abu Hurairah. Bahkan riwayat-riwayat tadi harus dipahami dalam konteks hadits Abu Hurairah. Orang-orang yang berpendapat bahwa shalat berjamaah merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah), mereka mengatakan bahwa kewajiban tersebut tidak dianggap terpenuhi dengan melakukannya di rumah. Pandangan yang sama dinukil pula dari Imam Ahmad sebagai sosok yang berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah kewajiban individu (fardhu ‘ain). Mereka memberi penjelasan atas pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa syariat shalat berjamaah dilaksanakan di masjid, dan ini merupakan sifat yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Untuk itu, hukum tersebut khusus berkenaan dengan masjid. Lalu dimasukkan di dalamnya tempat-tempat yang semakna dengan masjid, yakni tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat berjamaah.
لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاة (tidak ada yang mengeluarkannya kecuali shalat) Yakni tujuannya untuk melakukan shalat berjamaah.
فَإِذَا صَلَّى (apabila ia shalat) Ibnu Abi Jamrah berkata, “Maksudnya telah melakukan shalat dengan sempurna. Karena Rasulullah SAW telah berkata kepada seseorang yang tidak baik shalatnya, ‘Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat’ .”
فِي مُصَلَّاهُ (di tempat shalatnya) Yakni tempat di masjid yang dia tempati untuk melaksanakan shalat. Namun sepertinya lafazh ini berbicara di bawah konteks yang umum. Karena apabila seseorang berpindah ke tempat lain di masjid tersebut seraya tetap berniat menunggu shalat, maka ia seperti saat berada di tempat shalatnya.
اللَّهُمَّ اِرْحَمْهُ (Ya Allah, berilah rahmat kepadanya) Yakni mereka mengucapkan kalimat itu. Ibnu Majah memberi tambahan, اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (Ya Allah, terimalah taubatnya). Sementara pada jalur riwayat sebelumnya pada bab “Masjid-masjid Pasar” disebutkan اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ (Ya Allah, ampunilah ia).
Riwayat ini dijadikan dalil tentang keutamaan shalat dibanding amalan-amalan lainnya, berdasarkan hal-hal yang disebutkan yaitu shalawat (doa) para malaikat, permohonan mereka agar diberi rahmat, ampunan dan taubat. Selain itu hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang keutamaan orang-orang yang shalih dibanding para malaikat, karena orang-orang shalih mendapatkan kedudukan dengan ibadah mereka, sementara para malaikat sibuk berdoa dan memohon ampunan untuk mereka.
Kemudian hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini dijadikan sebagai dalil, bahwa jamaah bukan merupakan syarat sahnya shalat, karena sabda beliau SAW “Dibanding shalatnya sendirian” menunjukkan sahnya shalat yang dilaksanakan sendirian dan juga, karena lafazh “lebih utama” berarti keduanya sama dalam keutamaan tertentu. Ini berarti shalat sendirian juga memiliki keutamaan, sementara sesuatu yang tidak sah tidak memiliki keutamaan.
Al Qurthubi serta ulama-ulama lainnya berkata, “Tidak dapat dikatakan bahwa lafazh ‘lebih utama’ hanya untuk menetapkan keutamaan pada salah satu dari dua sisi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Furqan ayat 24 yang berbunyi, أَحْسَنُ مَقِيلًا (lebih indah tempat istirahatnya) karena penggunaan kalimat perbandingan dengan makna seperti pada ayat ini sangat jarang ditemukan, dimana kalimat perbandingan disebutkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan bilangan tertentu. Apabila kita mengatakan ‘Bilangan ini lebih banyak daripada yang ini’, maka sudah tentu masing-masing dari kedua bilangan merniliki jumlah tersendiri. Tidak bisa pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat sendirian dalam hadits adalah shalat seorang yang merniliki udzur, karena sabda beliau ‘daripada shalat seorang diri’ bersifat umum, mencakup shalat orang yang memiliki udzur (alasan syar’i) dan juga shalat orang yang tidak memiliki udzur. Maka memahaminya bahwa yang dimaksud adalah shalat orang yang memiliki udzur, membutuhkan dalil tersendiri. Di samping itu, keutamaan shalat berjamaah tetap didapatkan oleh orang yang shalat sendirian karena suatu udzur, sebagaimana hadits Abu Musa dari Nabi (Apabila seorang hamba sakit atau safar [bepergian], maka dituliskan untuknya amalan yang biasa ia lakukan saat sehat dan mukim [tidak bepergian]).”
Ibnu Abdul Barr mengisyaratkan bahwa sebagian ulama memahami shalat yang dimaksud adalah shalat nafilah (sunah). Kemudian dia membantah pandangan ini dengan mengemukakan hadits, (Shalat seseorang yang paling utama adalah shalatnya yang dilakukan di rumahnya kecuali shalat fardhu).
Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat jamaah memiliki keutamaan yang sama, baik jamaahnya banyak maupun sedikit. Karena hadits tersebut rnenunjukkan keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian, temasuk juga setiap yang dikategorikan shalat jamaah. Demikian pendapat sebagian ulama madzhab Maliki. Pendapat tersebut dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Ibrahim An-Nakha’i, dia berkata, “Apabila seseorang shalat bersama orang lain, maka keduanya dikatakan sebagai jemaah. Bagi mereka pahala dua puluh lima kali lipat.”
Pendapat ini dapat diterima pada batas minimal perolehan pahala tersebut, namun hal itu tidak menafikan adanya tambahan keutamaan apabila peserta shalat jamaah lebih banyak; teristimewa telah ada nash yang tegas menyatakan hal itu, yakni riwayat yang dinukil hnam Ahmad dan para penulis kitab Sunan yang di-shahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari hadits Ubay bin Ka’ab, dari Nabi SAW, (Shalat seseorang bersama orang lain lebih baik daripada shalatnya yang dilakukan sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lain lebih baik daripada shalatnya bersama satu orang. Semakin bertambah banyak semakin disukai oleh Allah).
Riwayat ini memiliki pendukung yang cukup kuat dalam – riwayat Ath-Thabrani dari hadits Qabbats bin Asyyam.
Dampak perbedaan pendapat ini tampak pada masalah mengulangi shalat berjamaah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa pahala shalat berjamaah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, maka mereka mengatakan disukainya mengulangi shalat jamaah yang dilakukan apabila ia mendapatkan jamaah lainnya shalat, untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Sedangkan mereka yang berpendapat shalat berjamaah tidak memiliki perbedaan, maka mereka tidak menyukai hal itu. Di antara mereka ada yang memberi perincian sebagai berikut:
“Ikut shalat jamaah lagi apabila shalat jamaah kedua dilakukan bersama orang yang lebih alim, atau lebih wara’, atau berada di tempat yang memiliki keutamaan.”
Bagian akhir pernyataan ini disetujui oleh Imam Malik, namun beliau membatasinya pada tiga masjid {Masjidil Haram (Makkah), Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Palestina) -ed}. Sementara yang masyhur dari beliau bahwa maksud dua masjid yang pertama adalah masjid Makkah dan masjid Madinah. Sebagaimana jamaah berbeda-beda dalam keutamaan karena faktor jumlah pesertanya atau yang lainnya, maka demikian pula halnya jamaah, sebagiannya lebih baik daripada yang lain. Oleh sebab itu, Imam Bukhari mengiringi bab tentang “keutamaan shalat jamaah” secara mutlak dengan bab tentang keutamaan shalat jamaah yang dikaitkan dengan shalat fajar. Hal ini beliau jadikan sebagai dalil bahwa batas minimal suatu jamaah adalah terdiri dari imam dan seorang makmum. Permasalahan ini akan dibahas pada bab tersendiri, insya Allah.
[1] Mafhum adad adalah makna implisit yang terkandung di balik penyebutan bilangan. Misalnya bila dikatakan “pahala shalat jamaah lebih (ada penambahan) dua puluh lima kali dibandingkan shalat sendirian,” berarti pahala tersebut tidak mungkin dua puluh enam, dua puluh tujuh dan seterusnya, penerj.
[2] Pernyataan ini kurang tepat, dan yang benar bahwa hadits itu mencakup seluruh shalat yang lima waktu, dan yang demikian itu merupakan tambahan karunia Allah SWT kepada mereka yang menghadiri shalat berjamaah.
[3] Pernyataan Imam An-Nawawi di tempat ini tidaklah tepat, dan yang benar bahwa shalat berjamaah hukumnya wajib baik saat mukim maupun safar, sebagaimana perbuatan Nabi SAW yang terus-menerus melakukan shalat jamaah berdasarkan sabda beliau SAW, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat”, serta firman Allah SWT, “Dan apabila engkau berada di antara mereka lalu engkau mendirikan shalat untuk mereka.” (Qs. An-Nisaa'(4): 102). Adapun keterangan tentang kelebihan shalat seseorang yang ia lakukan di tempat yang jauh dari pemukimam dan menyempurnakan ruku serta sujudnya daripada shalat seseorang yang ia lakukan secara berjamaah, tidak ada padanya hujjah yang menyatakan shalat jamaah tidak wajib saat safar. Sebab, dalil-dalil tentang wajibnya shalat jamaah saat safar bersifat muhkam (pasti). Oleh karena itu, tidak dapat ditinggalkan hanya karena dalil yang bersifat muhtamal (memiliki kemungkinan). Untuk itu nash ini -jika terbukti shahih- wajib dipahami di bawah konteks orang yang shalat di tempat jauh dari pemukiman sesuai kemampuannya -tanpa meninggalkan jamah selama hal itu memungkinkan- kemudian ia menyempurnakan ruku’ dan sujudnya meskipun ia hanya seorang diri bersama Tuhannya jauh dari manusia lainnya. Maka Allah SWT bersyukur atas keikhlasan dan perhatiannya terhadap shalat, sehingga pahalanya dilipatgandakan demikian rupa. Wallahu a’lam.
[4] Perkara yang dipermasalahkan oleh Al Qarafi adalah; bila dikatakan shalat berjamah lebih utama daripada shalat sendirian, maka konsekuensinya pahala amalan sunah lebih utama daripada pahala amalan wajib. Hal ini karena beliau berpandangan bahwa shalat berjamaah hukumnya sunah, seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar- penerj.
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 663-664 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 662 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 661 – Kitab Adzan - 30/08/2020