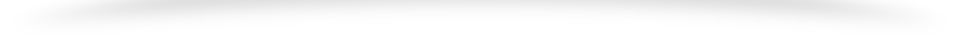PeciHitam.org – Hari ini siapapun bisa mengakses segala informasi dari belahan bumi manapun hanya dengan menggunakan smartphonenya. Hanya dengan menggoyang-goyangkan jempolnya, informasi yang dikehendaki pun terpapar.
Namun di sisi lain, banyak pula terdapat informasi yang terkesan ngawur dan tanpa dasar pertimbangan yang mumpuni. Hal ini tentu hanya akan memperkeruh suasana.
Seperti halnya konten ceramah yang beredar di jagad media sosial, seringkali ditemukan beberapa segmen, rubrik tanya jawab keislaman.
Dimana sang pembicara atau ustadz tersebut menjawab masalah agama dan hukum Islam tanpa pertimbangan keilmuan yang matang. Jawaban yang diberikan seolah sembrono, hanya asal cepat menjawab penanya atau audiens.
Segala macam persoalan agama seolah-olah bisa dijawabnya secara langsung. Barangkali agar terkesan pandai dan mumpuni dalam hal ilmu agama. Jika kita berkaca pada imam mazhab terdahulu, tidaklah demikian.
Justru para imam mazhab tersebut tidak selalu dapat menjawab secara langsung semua pertanyakan yang diajukan kepadanya. Beliau tidak segan untuk berkata, la adri yang artinya saya tidak tahu.
Hal ini disebabkan karena para imam mazhab sadar bahwa jawaban yang ia sampaikan bisa jadi justru akan menyesatkan masyarakat jika tidak dilandasi dengan wawasan dan pertimbangan hukummya secara komprehensif.
Dulu, Imam Malik pernah ditanya empat puluh persoalan agama dan hukum Islam. Beliau hanya menjawab 4 di antaranya. Sedangkan 36 sisanya, beliau menjawab: la adri (Saya tidak tahu)”. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi’I, ketika berbagai persoalan ditanyakan kepadanya, beliau juga menjawab: “Saya tidak tahu.”
Jawaban tersebut merupakan bentuk kehati-hatian imam mazhab dalam memberikan fatwa. Inilah etika menjawab pertanyaan yang kiranya paling ideal. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Majmu’ karya Imam An-Nawawi (Juz I: 73), Sahabat Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas ra, mengingatkan:
مَنْ أَفْتَى عَنْ كُلِّ مَا يُسْأَلُ فَهُوَ مَجْنُوْنٌ.
Artinya: “Barang siapa memberikan jawaban hukum (fatwa) terhadap setiap masalah yang ditanyakan kepadanya, maka dia adalah orang gila.” (HR Ath-Thabrani).
Oleh sebab itu, para ulama mazhab merumuskan syarat-syarat mufti (orang yang memberi fatwa), dengan syarat yang ketat berkaitan dengan keahlian (kapabilitas), dan integritas serta kredibilitas moral (akhlak).
Syarat ini pun seharusnya berlaku bagi seseorang yang ingin menjawab masalah agama ataupun hukum Islam dalam tanya jawab.
Daftar Pembahasan:
Syarat Bagi Mufti
Menurut Imam Al-Amidi asy-Syafi’i dalam kitabnya yang berjudul Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (Juz IV: 347), menyebutkan bahwa ada dua syarat wajib dan satu syarat anjuran bagi mufti, antara lain:
Pertama, ahli ijtihad, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil logika, dan dalil-dalil sama’i (wahyu) dan jenis-jenisnya, juga perbedaan tingkatannya terkait arah penunjukan dalil-dalil tersebut, serta mengetahui nasikh mansukh, dalil-dalil yang saling bertolak belakang dan tarjih terhadapnya, serta mengetahui tata cara merumuskan hukum dari dalil-dalil itu.
Kedua, bersifat adil dan terpercaya, sehingga jawaban hukum yang disampaikannya dapat dipercaya. Atas dasar inilah orang fasik tidak sah fatwanya.
Ketiga, syarat anjuran, dalam berfatwa itu tujuannya untuk memberikan arahan dan petunjuk kepada publik mengenai hukum syara’, bukan motif atau orientasi riya’ (pamer) dan sum’ah (ingin tenar). Mempunyai sifat tenang dan berwibawa, agar orang yang mendengarkannya bersemangat menerima yang ia sampaikan, dan menjaga diri dari menyakiti manusia, serta menjauhkan sikap yang dapat berakibat orang berpaling darinya.
Syarat Mujtahid (Orang yang Memberi Ijtihad)
Jika seseorang ingin memberikan ijtihad, fatwa ataupun menjawab masalah agama, ada banyak syarat yang harus ia penuhi terlebih dahulu. Setidaknya ada delapan syarat mujtahid, ditambah satu syarat bagi mufti, antara lain:
- Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ma’ani, bayan dan uslub bahasa, karena Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab;
- Mengetahui makna ayat-ayat hukum Al-Qur’an (sekitar 500 ayat hukum);
- Mengetahui hadis-hadis hukum, yaitu sekitar 500 (versi Imam Al-Mawardi), 3000 hadis (versi Ibnul ‘Arabi), bahkan 300 ribu atau 500 ribu hadis (versi Imam Ahmad);
- Mengetahui perihal ilmu nasikh dan mansukh Al-Quran dan Sunnah, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu;
- Mengetahui tempat-tempat ijma’;
- Mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya, ‘illat hukum dan metode istinbat-nya dari nash-nash, mengetahui kemaslahatan manusia dan prinsip-prinsip universal bagi syara’;
- Menguasai ilmu ushul al-fiqh;
- Paham maqasid asy-syariah yang bersifat universal (fahmu maqasid asy-syariah al-‘ammah);
- Berintegritas, bersifat adil, yakni menjauhi kemaksiatan yang merusak sifat adil. Sungguh pun ketatnya syarat ijtihad itu, ijtihad partikular mengenai suatu bidang tertentu (tajazzu’ al-ijtihad), bagi orang yang menguasai satu bidang tertentu, bukan bidang yang lain, boleh berijtihad dalam lingkup bidangnya itu.
Tiga Perangkat Metodologis
Merujuk tulisan Ustadz Ahmad Ali MD pada laman islam.nu.or.id, ketika seseorang hendak menjawab pertanyaan hukum, ijtihad maupun fatwa, setidaknya ada tiga perangkat metodologis yang harus diperhatikan, antara lain:
Pertama, Tahqiq al-Manath, yakni upaya mengidentifikasi dan memverifikasi substansi obyek hukum sehingga dapat menghindari kesalahan teknis dalam penyesuaian antara satu hukum dengan obyeknya. Menekankan urgensi seorang mujtahid memahami dan mendalami sesuatu/peristiwa (kasus) yang sedang terjadi
Kedua, I’tibar Ma’alat al-Ahkam, yakni mempertimbangkan dan memantau kondisi aplikasi hukum yang telah ditempuh pada perangkat Tahqiqul Manath. Memahami dan mempertimbangkan dampak atau implikasi hukum yang akan terjadi (mutawaqqa’): menarik maslahat atau justru menyebabkan mafsadat.
Ketiga, Mura’at al-taghayyurat, yakni memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam realita, karena kebijaksanaan hukum dapat berubah berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, motivasi, dan adat-istiadat/tradisi. Dalam konteks ini, perlu mura’at al-khilaf, yakni mempertimbangkan ikhtilaf ulama mengenai suatu hukum.
Lima Parameter Memahami Hukum
Lebih lanjut, beliau juga menambahkan lima parameter memahami hukum yang dirumuskan oleh Prof Dr Khalid Abul Fadhl (pakar hukum Islam kontemporer) dalam karyanya Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women.
Lima parameter ini dibutuhkan agar pemahaman, menjawab masalah agama, dan penerapan hukum Islam itu, bersifat otoritatif dan tidak otoriter (sewenang-wenang).
Pertama, melakukan kejujuran (honesty), yakni seseorang dalam merumuskan dan/atau menjawab pertanyaan hukum tidak bersikap pura-pura memahami sesuatu yang tidak diketahuinya, tetapi bersikaplah jujur mengenai wawasan dan kemampuannya dalam memahami hukum.
Kedua, kesungguhan (diligence), yakni penuh tanggung jawab agar tidak mencederai yang berhak menerima hak.
Ketiga, melakukan pertimbangan secara menyeluruh (comprehensiveness), yakni mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
Keempat, melakukan rasionalitas (reasonableness), yakni melakukan interpretasi (penafsiran) dan menganalisis hukum itu secara rasional (logis).
Kelima, mengendalikan diri (self-restraint), yakni harus mengenal batasan peran yang dimiliki, sehingga dapat menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan mengenai suatu persoalan ketika bukti-buktinya tidak mencukupi.
Melihat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi ketika akan menjawab masalah agama ataupun hukum Islam di atas, tentunya tujuannya agar dapat menyaring dan menyeleksi agar jawaban yang disampaikan tidak sembarangan ataupun ngawur.
Tidak ada lagi ustadz karbitan yang bicara seenaknya, seperti mengharamkan genre film, mengharamkan sebuah game, menuduh lagu anak-anak anti Islam dan sebagainya.
Oleh karena itu, posisi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) menjadi satu contoh dan model lembaga yang penting dan otoritatif untuk dimintai pandangan hukumnya terkait masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat. Ash-Shawabu Minallah.