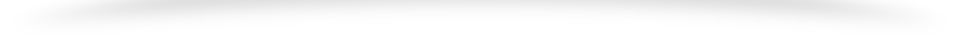Pecihitam.org – Khilafiyah sebenarnya hal biasa yang selalu muncul dalam kehidupan dunia umat manusia, baik dalam sosial maupun agama. Hanya saja kita orang awam seringkali kaget, karena sebelumnya tidak mengerti bahwa beda pendapat bisa terjadi pada siapa saja, dari politikus hingga rakyat biasa, dari orang awam hingga pemuka agama, tak terkecuali ulama.
Sejatinya, yang terpenting adalah bukan bagaimana melenyapkan perbedaan, tapi bagaimana kita menyikapinya, terutama di zaman internet ini, dimana informasi dengan begitu mudah didapat bahkan dipaksa untuk menerimanya lewat media sosial. Informasi yang kadang benar tidaknya masih meragukan.
Bagaimana Ahlusunnah Wal Jamaah menyikapi khilafiyah? Akan coba kita telaah bersama.
Definisi Khilafiyah
Khilafiyah berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata “ikhtilaaf”, yaitu dari kata kerja tiga huruf “khalafa” yang diantara terjemahnya “berbeda, berlainan”. Hanya saja ada beda dalam penggunaannya.
Kata “khilafiyah” yang berasal dari “khaalafa” (bertambah huruf alif setelah fa’ fi’l-nya) digunakan untuk menyebut masalah atau sesuatu yang menimbulkan perbedaan, sedangkan “ikhtilaaf” yang berasal dari kata “ikhtalafa” (bertambah huruf alif di awal dan huruf ta antara fad dan ‘ain fi’l-nya) digunakan untuk menyebut perbedaannya.
Bila kita bandingkan dengan bahasa Inggris, maka kata “khilafiyah” mendekati arti kata “controversial”, yaitu sesuatu yang sifatnya menimbulkan perbedaan dan memancing perdebatan. Kata ini yang kemudian diserap dan dibakukan dengan penulisan “kontroversial”.
Adanya Ikhtilaf Dan Khilafiyah Niscaya
Dalam sejarah kehidupan para ulama, tak jarang kita menemukan adanya fatwa atau sikap mereka yang menimbulkan perdebatan sesama ulama. Sejak zaman generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ‘anhum, hingga generasi selanjutnya.
Ada banyak contoh kasus dalam hal ini. Baik yang sifatnya politik maupun pendapat keagaaman. Contoh dalam politik adalah diangkatnya Sayyidina Abu Bakr sebagai khalifah telah memunculkan kontroversi antara ahlul bait dengan mayoritas sahabat, sehingga kemudian melahirkan bibit-bibit Syi’ah dalam Islam. Contoh dalam pendapat keagamaan diantaranya tentang qiraat (bacaan) al-Qur’an.
Al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan, “Masalah khilafiyah sudah terjadi diantara para sahabat, tabi’in, dan ulama sesudah mereka radhiyallahu anhum” (2:24). Dalam al-Qur’an disebutkan :
وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ
“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat” (QS Hud : 118).
Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengomentari “Maksudnya, perselisihan tetap ada di kalangan manusia dalam masalah agama dan akidah mereka menjadi terbagi ke dalam berbagai madzhab dan pendapat.”
Hal ini menunjukkan bahwa adanya sesuatu atau perkara yang memunculkan beda pendapat adalah hal yang niscaya, karena Allah tidak menghendaki umat manusia hanya dalam satu saja, tanpa ada perbedaan diantara mereka.
Kendati ikhtilaaf adalah hal yang niscaya, namun Allah memberi pengecualian pada ayat selanjutnya :
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ
“Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.”
Ini menunjukkan bahwa dalam menyikapi khilafiyah ada orang-orang justeru mendapat rahmat Allah. Inilah yang akan kita diskusikan kali ini. Yaitu bagaimana menyikapi khilafiyah agar menjadi sebuah rahmat Allah.
Penyebab Terciptanya Khilafiyah Dan Ikhtilaf
Ada banyak faktor terciptanya khilafiyah yang memicu lahirnya ikhtilaf. Diantaranya:
1. Perbedaan paham atas suatu dalil.
Contoh dalam hal ini adalah tentang hukum berkurban. Diriwayatkan bahwa Baginda Rasulullah shallallahu ‘alaih wa aalih wa sallam tidak pernah meninggalkan kurban, baik ketika mukim maupun musafir.
Menurut Imam Maalik dalam suatu riwayat, Rabi’ah, al-Awzaa’i, al-Laits bin Sa’d dan Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat, hukum berkurban wajib. Namun dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberi rincian bahwa jika seseorang memiliki harta senisab maka wajib berkurban bila tidak maka tidak wajib.
Kewajibannya hanya pada orang yang bermukim dan tidak pada musafir. Menurut mayoritas fuqaha, berkurban hukumnya sunnat muakkad. Baik fuqaha di kalangan sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ibn Mas’ud, Sayyidina Ibn ‘Abbas dan Sayyidina Ibn ‘Umar. Inilah yang diperpegangi madzhab Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan menurut pendapat “masyhur” dalam madzhab Imam Maalik.
Bahkan diriwayatkan oleh at-Thahawi bahwa Imam Abu Yusuf dan Muhammad (asy-Syaibani) murid Imam Abu Hanifah juga berpegang pada pendapat ini.
2. Perbedaan penerimaan atas suatu riwayat.
Perbedaan ini diantaranya karena seorang mujtahid tidak meyakini kesahihan riwayat suatu hadits yang diyakini oleh mujtahid lainnya. Ada banyak contoh mengenai hal ini.
3. Perbedaan prinsip dan metode dalam istidlal (pendalilan).
Perbedaan ini berada di ranah ushul fiqh. Ada banyak kitab disusun para ulama yang membahas masalah ini. Diantaranya “Asbaab al-Ikhtilaaf al-Fuqahaa” susunan Dr. Musthofa Ibrahim az-Zilmi. Dalam kitab ini penyusun menelusuri akar perbedaan delapan madzhab besar dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, Zhahiri, Syi’ah Imamiyah dan Syi’ah Zaidiyah) dan menguraikannya dari sudut pandang prinsip dan metode pendalilan.
4. Perbedaan tingkat pengetahuan dan penguasaan serta wawasan.
Bila para ulama generasi Salaf umumnya berbeda karena beda memahami dan penerimaan atas dalil ataupun karena beda metode memahami dalil, maka perbedaan yang muncul pada generasi akhir umumnya disebabkan beda tingkat pengetahuan dan penguasaan serta wawasan.
Misal ketika Gus Dur mengusulkan “Assalamu’alaikum” diganti dengan ucapan “Selamat Pagi/Siang/Malam”, banyak orang ribut dan menyalahkan. Padahal itu karena ketidaktahuan mereka bahwa dalam fiqh ke-sunnah-an mengucap salam tidak mesti dengan lafazh “Assalaamu’alaikum”, bisa saja dengan redaksi dan bahasa berbeda.
Misal lainnya ketika Kyai Said Agil Siradj mengatakan makin panjang jenggotnya makin bodoh akalnya. Tidak sedikit yang meributkan. Padahal hal ini sudah dibahas para ulama masa silam, diantaranya al-Imam al-Ghazali dalam Ihyaa ‘Uluumiddin.
5. Unsur Politik.
Perbedaan karena unsur politik sudah terjadi sejak pasca wafatnya Baginda Rasulullah shallallahu ‘alaih wa aalih wa sallam. Sejarah mencatat perbedaan antara Anshar dan Muhajirin di Tsaqifah Bani Sa’idah tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin ummat terjadi bahkan ketika jasad Baginda Nabi belum dikuburkan.
Perbedaan yang meski melahirkan kesepakatan diangkatnya Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ‘anh namun tak urung menyebabkan adanya orang-orang yang murtad dan ada yang membelot dengan cara tidak mau menyetorkan zakat kepada pemerintah (Khalifah).
Dalam Babad Demak dikisahkan bahwa pasca wafatnya Sultan Trenggono, para Walisongo berbeda pilihan politik. Sunan Giri mendukung Sunan Prawoto, Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang (Adipati Jipang), dan Sunan Kalijaga mendukung Hadiwijaya (Jaka Tingkir).
6. Unsur kedengkian.
Unsur kedengkian termasuk diantara pemicu ikhtilaf. Kita tidak perlu membahas lebih jauh tentang ini.
Dari enam penyebab diatas, empat yang pertama adalah khilafiyah yang bisa diterima dan ikhtilaf atasnya bisa ditoleransi. Adapun yang terakhir yaitu unsur kedengkian maka mutlak dihindari. Yang harus diwaspadai adalah adanya unsur kedengkian yang tersembunyi dan berlindung dibalik lima alasan sebelumnya. Yang harus dipertimbangkan adalah unsur politik.
Menyikapi Khilafiyah
Dalam menyikapi khilafiyah atau sesuatu yang mengundang kontroversi kita harus bijak dan meniru para ulama Ahlussunnah Waljamaah. Saya klasifikasikan menjadi tiga:
1. Kelas ulama.
Idealnya, seorang ulama menyikapi khilafiyah dengan mengkaji dan meneliti, sejauh mana tepat atau melencengnya perkara yang dikontroversikan dari prinsip dan dalil-dalil agama, juga kondisi sosial masyarakat, untuk kemudian memberi pandangan yang bersifat mashlahat bagi semua umat manusia. Inilah prinsip ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Selama khilafiyah tersebut masih bisa ditemukan landasan kebenarannya, maka tidak perlu untuk di-ikhtilaf-kan.
Terpilihnya Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu ‘anh meski awalnya perkara khilafiyah karena ada yang menginginkan kekhalifahan berada pada golongan Muhajirin, ada yang ingin dari golongan Anshar, ada yang ingin masing-masing punya pemimpin, dan ada pula yang ingin dari ahlu bait Nabi, namun para sahabat dan keluarga Nabi akhirnya menerima keabsahan dan berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakr.
Bersedianya Sayyidina ‘Ali berdamai dengan Sayyidina Mu’awiyah pada perang Shiffin menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Sekelompok orang yang semula pro Sayyidina Ali berontak dan keluar menjadi “Khawarij”. Kelompok lain yang juga pro Sayyidina Ali menyimpan dendam berkepanjangan dan menjadi “Rafidhi”. Tapi ada sekelompok yang meski mengakui kebenaran ada pada Sayyidina Ali, namun tidak memusuhi Sayyidina Mu’awiyah. Toh Sayyidina Ali saja mau berdamai, kenapa pengikutnya tidak. Kelompok inilah yang kelak menjadi bintang petunjuk bagi Ahlussunnah Waljamaah.
Di Indonesia, para ulama NU meski pernah ikut merumuskan Piagam Jakarta namun karena ini perkara khilafiyah dalam berbangsa dan bernegara maka tidak memaksakan diberlakukan dan menerima Pancasila sebagai dasar negara pada tahun diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia 1945. Padahal kala itu terjadi ikhtilaf luar biasa antara kelompok agamis dengan nasionalis.
Anjuran kembali ke UUD 1945 untuk menggantikan UUD Sementara 1950 adalah perkara khilafiyah yang mengancam perpecahan Indonesia, maka meski mulanya NU pada sidang konstituante tahun 1958 bersama kelompok agamis memperjuangkan syariat Islam dalam undang-undang negara, namun kemudian setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, NU menerima dekrit Presiden Soekarno untuk memberlakukan kembali UUD 1945.
Pemaksaan asas tunggal adalah salah satu khilafiyah di zaman orde baru. Khilafiyah yang menimbulkan ikhtilaf antar ulama yang bahkan dalam satu organisasi. Di tubuh NU sendiri ada yang menolak dan ada yang menerima. Ada kubu Cipete yang dimotori KH. Idham Khalid dan ada kubu Situbondo yang dipimpin Kyai As’ad Syamsul ‘Arifin.
Namun akhirnya pada munas tahun 1983 dan Muktamar 1984 NU menerima Pancasila sebagai asal tunggal bagi seluruh ormas dan partai politik. Meski ulama NU punya pandangan sendiri, namun tidak memaksakan pandangannya. NU berpegang pada prinsip Ahlussunnah Wal Jama’ah.
Prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah adalah berpegang pada mashlahat dan senantiasa memilih jalan moderat. Dimana ada kemashlahatan dan masih tidak melenceng dari prinsip dasar agama Islam, maka ulama Ahlussunnah Waljamaah akan ikut pada yang mashlahat, mengambil jalan tengah (moderat) dan tidak memaksakan kepada kelompok/orang yang ijtihadnya yang berbeda. Al-Khuruj min al-Khilaf; Mustahab (keluar dari kontroversi, disunnahkan).
2. Kelas penuntut ilmu.
Kelas ini adalah jenjang menengah, yaitu sudah naik dari level awam namun masih belum mencapai tahap ulama. Idealnya seorang penuntut ilmu ketika menemukan sesuatu yang kontroversial juga ikut langkah para ulama, yaitu mengkaji dan belajar menelusuri akar perbedaan.
Namun, karena masih belum luas wawasannya, belum dalam kajiannya, belum tajam pisau bedahnya, para penuntut ilmu pada akhirnya ikut pendapat para ulama atau gurunya.
3. Kelas awam.
Adapun kelas awam yang tidak memiliki kemampuan mengkaji dan meneliti, maka lebih baik diam dan tak usah memberi komentar. Karena komentar orang awam hanya akan melahirkan kerisuhan. Kelas awam umumnya masih dikendalikan emosi dan nafsu, bukan nalar berdasar ilmu.
Sebab itu yang dijaga adalah emosi dan kesadaran diri bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang perkara yang diperdebatkan. Ikuti saja pendapat para ulama yang diyakininya.
Sebuah adagium yang dinisbatkan kepada sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sepatutnya senantiasa menjadi peringatan, “Law Sakatal Jaahil, Ma ikhtalafan Naas” (seandainya orang-orang bodoh tidak ikut berkomentar, niscaya tidak ada perpecahan diantara manusia).
Menyikapi Ikhtilaf/Kontroversi
Menyikapi ikhtilaf atau kontroversi adalah dengan senantiasa berbaik sangka dan menyadari bahwa perbedaan itu hal yang niscaya. Tidak gegabah menuduh salah, apalagi mendakwa sesat. Terutama bila yang ikhtilaf itu ulama. Tentu mereka punya landasan dan dalilnya ketika memutuskan suatu perkara. Meski ada yang berpandangan sempit dan sebaliknya ada yang terbuka.
Karenanya, ketika ada ikhtilaf atas khilafiyah yang tidak mungkin diseragamkan, maka ulama Ahlussunnah Wal Jamaah mengakui dan menghormati semua orang atau kelompok yang beda pendapat tersebut, meski memilih salah satu untuk diperpegangi.
Ini tercermin pada pengakuan atas madzhab empat dalam fiqh, madzhab Asy’ari dan Maturidi dalam akidah, dan beragam tarekat dalam bertasawwuf. Ahlussunnah Waljama’ah tidak mencela mereka yang berbeda pendapatnya, meski tidak mengikutinya. Bahkan ulama Ahlususnnah Waljama’ah berupaya meredam ikhtilaf dengan membiarkannya dalam khilafiyah. Karena bila dipaksakan dalam satu pendapat, justeru akan memancing perpecahan dan penentangan dari mereka yang merasa dipaksa meninggalkan pendapatnya.
Diriwayatkan bahwa kitab Muwatha Imam Malik (93 – 179 H) pernah tiga kali diminta untuk dijadikan kitab undang-undang dasar negara, yaitu oleh Ja’far bin Manshur (131 – 163 H), al-Mahdi (163 – 173 H) dan Harun ar-Rasyid (173 – 197 H), namun ketiga permintaan beliau tolak karena tak ingin mempersulit umat Islam yang berbeda pandangan dan madzhabnya. Biarlah umat bebas memilih, ulama mana yang diikutinya.
Hari ini, kita menyaksikan adanya orang-orang yang memaksakan pendapat dan keyakinan kelompoknya. Memprovokasi pengikutnya untuk bersikap keras kepada kelompok yang berbeda. Jelas, sikap ini bukan cara Ahlusunnah Waljama’ah.