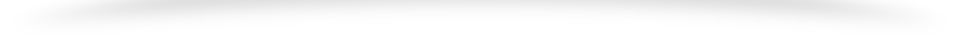Pecihitam.org – Pada dasarnya, membaca perjalanan hidup Sayyid Quthb akan menimbulkan perasaan yang bercampur-aduk. Pada satu sisi, kita disuguhi gambaran pergolakan psikologis, intelektual, aktivisme, penderitaan, keteguhan dan kesalehan. Di sisi lain, dampak logis dari tulisan-tulisannya yang membawa pada anarki, ekstremisme, takfiri dan jihadisme cukup membuat kening berkerenyit dalam.
Sayyid Qutb menulis karyanya Fi Zhilal al-Quran (Dalam Bayangan al-Quran), Ma’alim fi al-Thariq (Rambu-rambu di Jalan). Bagi para pengikut Ikhwan al-Muslimun, tulisannya merupakan inspirasi yang menerangi. Akhir hayat Sayyid Quthb di tiang gantungan boleh jadi juga merupakan cita yang diimpikan. Namun, ada problem besar dalam pemikiran Sayyid Quthb.
Usamah Sayyid al-Azhari dalam bukunya al-Haqq al-Mubin fi Radd ‘ala man tala’aba al-Din (Kebenaran yang Benderang: Menolak Pihak yang Memanipulasi Agama) (2015) menyoroti tentang Sayyid Quthb dan aliran ekstremnya (tayârat al-mutatharifah). Versi terjemahan bahasa Indonesia buku Usamah ini diberi judul Islam Radikal.
Bagi Usamah dapat disimpulkan bahwa pemikiran utama yang menjadi pondasi semua konsep kelompok-kelompok Islam ekstrem ini adalah konsep hakimiyah. Konsep ini menjadi dasar dari seluruh rangkaian pemikiran kelompok tersebut dengan aneka pendapat, pemahaman dan cabang-cabangnya.
Konsep hâkimiyah ini menurunkan apa yang dinamakan konsep syirik hâkimiyah dan tauhid hâkimiyah. Jelas konsep ini berbeda tajam dengan konsep syirik jalli (besar), syirik khafi (tersembunyi), dan syirik khafi wa-‘lkhafi (sangat tersembunyi) khas para sufi. Bila konsep hâkimiyah berenang di wilayah etiko-politis, maka konsep syirik para sufi menyelam di ranah etiko-religius.
Dengan bertolak dari konsep hâkimiyah Sayyid Quthb bersama saudaranya Muhammad Quthb meyakini bahwa mereka yang memegangi konsep ini adalah mukmin sejati yang disebutnya al-‘ushbah al-mu’minah.
Kelompok al-‘ushbah al-mu’minah ini percaya bahwa Allah memiliki janji terhadap orang yang bergabung dengan golongan mereka. Pihak lain yang tidak bergenggam pada konsep hâkimiyah adalah kaum jahiliyah meskipun itu umat Islam. Al-‘ushbah al-mu’minah merasa bahwa mereka sangat berbeda, dan berpikir bahwa mereka lebih baik dari umat Islam lainnya.
Dari pandangan semacam ini pula lahir keyakinan tentang keniscayaan perbenturan antara al-‘ushbah al-mu’minah dengan umat Islam lainnya demi menegakkan khilafah, tentang kekuasaan yang harus direbut (tamkîn), tiadanya tanah air, takfîr, dan pusparagam konsep lainnya yang menjelma menjadi teori utuh di nalar para penganut kelompok tersebut.
Usamah membulatkan lima faktor yang menjadi dasar paradigma takfiri, hâkimiyah yang digagas Sayyid Qutb.
Pertama, salah memahami ayat. Disebut dengan hâkimiyah karena Sayyid Quthb mengambil dasarnya dari gagasan al-Quran di Surah al-Maaidah: 44, yang berbunyi: “Barangsiapa yang tidak berhukum (lam yahkum) menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir.”
Sayyid Quthb mengikuti pemahaman Abu al-A’la al-Mawdudi dalam menafsirkan ayat ini. Mawdudi mengafirkan orang yang tidakmenerapkan hukum Islam, meskipun orang tersebut meyakini bahwa ayat itu benar dan berasal dari Allah.
Baginya orang yang tidak menerapkan syariat dihukumi kafir, meskipun orang tersebut tidak dapat menerapkan karena satu dan lain sebab. Bukan hanya dari Mawdudi, benih-benih pemikiran takfiri didapat Quthb juga dari tulisan-tulisan Hasan al-Banna. Ini adalah pandangan yang sempit, ketat dan dangkal. Tergesa-gesa dalam mengafirkan dan memperluas ranah cakupan hal yang tidak relevan.
Imam Abu Muhammad bin Athiyah al-Andalusi (w.1148 M) di dalam kitabnya al-Muharrar al-Wajiz mengatakan bahwa redaksi ayat al-Maidah:44 tersebut bukan berbentuk umum, melainkan musytarak (homonim) yang sering terjadi pada hal-hal khusus.
Karena itu, bagi Ibn Athiyah para pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah sama sekali tidak dianggap kafir. Imam Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) dalam al-Mustasyfa juga berpendapat yang senada dengan Ibn Athiyah saat mengomentari ayat yang sama.
Siapa pun yang menelusur kitab-kitab para imam yang menguasai berbagai cabang disiplin keilmuan skolastis Islam tentu akan menjumpai aneka pendapat dan orientasi terhadap Surah al-Maaidah: 44 tersebut.
Kesemua pendapat dan orientasi mereka akan berpangkal pada nama-nama para sahabat semisal Ibn ‘Abbas, Ibn Mas’ud, al-Barra bin Azib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim al-Nakha’i, al-Sudi, al-Dhahhak, Abu Shalih, Ibn Mijlaz, Ikrimah, Qatadah, Amir, Sya’bi, ‘Atha dan Thawus.
Hal yang sama bisa ditemui dalam karya-karya Imam al-Thabari, Imam Ibn Katsir, Imam al-Qurthuby, Imam Fakhruddin al-Razy, Thahir bin Asyur, sampai Syeikh Sya’rawi. Kontras dengan nalar para sahabat dan para imam di atas, seturut telusuran Usamah, paradigma takfiri Quthb hanya bisa ditemui dalam khazanah aliran Haruriyah atawa Khawarij.
Kedua, salah aqidah. Di dalam Fi Zhilal al-Quran acap kali Sayyid Quthb mengulang-ulang ungkapan rekaannya sendiri dan menjadikannya kaidah baku. Ungkapannya berbunyi “Hâkimiyah adalah bagian paling fundamental dari sifat-sifat ketuhanan.”
Ungkapan ini tak bakal ditemui dalam ucapan para ulama ahli kalam dan akidah. Sayyid Quthb yang menggantikan bagian fundamental sifat keesaan Allah yang sempurna dan mutlak dengan hâkimiyah, maka akibatnya akan muncul pemahaman yang serba menghakimi dan merasa paling benar sendiri. Dampak psikisnya sungguh luar biasa.
Ketika ia melihat sebagian kaum muslimin tidak menjalankan hal-hal furu’iyyah fikih maka ia bisa serta-merta menghukuminya sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah SWT.
Hal ini menjadi tekanan psikologis berat sendiri baginya sehingga tidak segan lagi mengafirkan orang lain dan bahkan melebar mengafirkan umat Islam.
Padahal perbedaan tidak menyentuh hal paling fundamental dari ushuluddin (dasar-dasar agama), yakni tauhid, tetapi hanya persoalan furu’iyyah. Persoalan furu’iyyah dianggap menjadi persoalan ushuluddin, tentu ada cara pemahaman yang salah di sini.
Ketiga, manakala berbicara tentang undang-undang yang berlaku di pengadilan dan penerapan undang-undang tersebut dalam peradilan Sayyid Qutb menghukuminya sebagai tindakan berhukum dengan hukum selain hukum Allah Ta’ala.
Dampaknya bisa diraba, umat Islam dianggap kafir seluruhnya. Syariat Islam yang terkait dengan praktik-praktik keagamaan dan kebudayaan tak memiliki nilai dalam pandangannya, semua diukur dengan konsepnya sendiri, hâkimiyah.
Keempat, salah paham sejarah hukum Islam. Saat menafsirkan firman Allah yang berbunyi: “Tidak ada hukum melainkan hukum Allah.” (QS. Yusuf: 40), para ulama Ushul Fikih dan ahli Tafsir memahami bahwa hanya Allah semata yang memiliki hak prerogatif memutuskan halal, haram, sunah, makruh, mubah, sah, rusak, serta terlaksana dan tidak.
Para nabi, rasul dan ijmak umat Islam hanyalah sebagai perantara untuk menjelaskan perihal hukum yang telah ditetapkan Allah SWT dalam setiap permasalahan. Di sini dipahami adanya dua ranah yang relatif terpisah, yakni akidah dan fikih.
Bagi para ulama setelah menegaskan hak prerogatif Allah, baru tafsir hukum masuk ke wilayah fikih yang terkait erat dengan sebab, ‘illat, syarat, dan mani’. Dus, muncullah interaksi masyarakat dengan pedoman-pedoman fikih yang sebagian dijalankan dengan baik dan sebagian lagi terjadi kekurangan dan kesalahan.
Sayyid Quthb main langsung ke akidah. Masyarakat yang dianggap kurang sempurna menerapkan hukum syariat langsung divonis kafir karena menentang sifat utama Allah, hâkimiyah. Ini kesalahan fatal Quthb. Dia masuk ke detail ilmu kalam dan ushul fikih, padahal dia tidak menguasainya dengan baik. Mengapa dia tidak menguasai disiplin dasar di atas?
Faktornya karena memandang minor sejarah intelektual Islam sebagai wawasan jahiliah. Ini tergambar dengan tegas dalam ucapannya di Ma’alim fi al-Thariq: “Bahkan banyak yang kita anggap sebagai wawasan Islam, rujukan Islam, filsafat Islam, dan pemikiran Islam, merupakan produk dari masyarakat jahiliah ini.”
Sayyid Quthb sama sekali tidak mengetahui dan memahami bab yang sangat penting dan detail dalam ilmu ushul fikih, yakni bab ‘awaridh al-ahliyyah, ihwal yang menyebabkan seseorang tidak dikenakan konsekuensi hukum syariat karena sejumlah hal.
Kelima, Sayyid Quthb berkesimpulan bahwa risalah agama Islam telah mengalami keterputusan. Ini merupakan pandangan yang aneh dan janggal. “Sesungguhnya eksistensi umat Islam sudah terputus sejak beberapa abad yang lalu,” ujarnya di dalam Ma’alim fi al-Thariq.
Sulit menemui ucapan ini pada para intelektual yang menguasai berbagai cabang disiplin keilmuan Islam. Ucapan ini hanya bisa muncul dari orang yang berwawasan sempit atau sengaja menyempitkan wawasannya.
Bila umat Islam dianggap tidak ada selama berabad-abad, lantas apakah Sayyid Qutb sendiri dan kelompoknya saja yang muslim? Pertanyaan ini layak diajukan kepadanya.
Terakhir, paradigma yang dibangun Sayyid Quthb dibangun di atas estetikanya pribadi. Ia berpijak pada asumsi, perasaan, dan paradigmanya sendiri. Ia menjauh dari metodologi ilmiah yang dikembangkan selama berabad-abad oleh ulama dan intelektual Islam. Dengan mencap sebagai jahiliah, ia berpaling dari produk ilmiah tradisi intelektual Islam. Baginya pokok ajaran Islam adalah hâkimiyah alih-alih tauhid. [ ]
Penulis: Riza Bahtiar (Akademisi UIN Syarif Hidayatullah)
Editor: Resky S
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 663-664 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 662 – Kitab Adzan - 30/08/2020
- Hadits Shahih Al-Bukhari No. 661 – Kitab Adzan - 30/08/2020