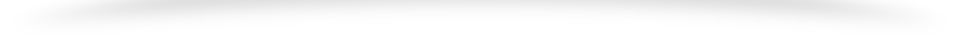Pecihitam.org – Suatu waktu saya menghadiri sebuah upacara yang mengharuskan seluruh undangan mengenakan pakaian jas lengkap beserta kemeja, dasi dan sepatu kantor yang mengkilat. Ini menandakan upacara itu sangat resmi dan bernuansa modern namun sakral. Sesampainya di tempat upacara perhatian saya tertuju pada penampilan seorang kawan yang turut hadir.
Seperti saya ia mengenakan jas, terlihat bersahaja. Rambutnya tersisir rapi meski sebagian kepalanya tertutup songkok. Tampilannya biasa, kecuali sebentuk bulatan-bulatan kecil terlihat di bagian belakang leher. Saya dan sepertinya semua hadirin tahu bahwa kawan itu belum lama sebelumnya berbekam.
Bekam adalah teknik pengobatan tradisional untuk mengeluarkan racun dan zat berbahaya lainnya dari tubuh. Cangkir-cangkir dipanaskan lalu ditempel di atas beberapa bagian permukaan kulit.
Lalu ketika cangkir-cangkir itu mendingin, udara dingin di dalamnya akan menarik kulit dan mengakibatkan permukaan kulit membentuk bekas-bekas bulat merah karena pembuluh darah merespon perubahan tekanan.
Sepintas bulat-bulat merah itu layaknya noda di bagian tubuh yang terbuka, sehingga mengurangi kerapian dan kebersihan penampilan untuk menghadiri sebuah acara resmi. Tapi tidak bagi kawan kita tadi dan hadirin yang melihatnya, kalaupun mereka memperhatikan.
Sebab, bekam dikenal sebagai salah satu teknik pengobatan ala Rasulullah, diketahui dan dipraktekkan oleh beliau. Bekam karena itu bersifat syar’i (sesuai syariat) dan berbekam dianggap mengikuti sunnah Nabi.
Karena telah mengikuti sunnah Nabi dan berbekam itu syar’i, mereka yang mempraktekkannya tidaklah menganggap bekas-bekas bekam sebagai noda di badan. Justru keberadaanya melahirkan rasa kedekatan dengan diri Nabi dan rasa kesucian serta kebanggaan.
Kini bekas bekam menjadi simbol penanda kesalihan lainnya, setelah janggut, tanda hitam di jidat dan bekas luka di sekujur tubuh bagi kalangan Syi’ah yang memperingati tragedi Karbala.
Inipun menjadi sesuatu yang menarik karena biasanya kesalihan disimbolkan melalui pakaian, seperti sorban, gamis dan jilbab, namun yang ini melekat dan menjadi bagian dari tubuh.
Berbekam dianggap sebagian muslim sebagai salah satu teknik pengobatan ala Rasulullah dan pengobatan itu syar’i, begitu pula meminum obat berbahan dasar habbatussauda, segala multivitamin dari ekstrak kurma dan lain sebagainya. Klaim syar’i tersebut bukan tanpa alasan, sebab jenis pengobatan semacam itu dirujukkan kepada hadis-hadis sahih.
Seiring dengan mencuatnya populisme Islam sebagai akibat dari pertumbuhan masyarakat kelas menengah muslim sejak kurang-lebih 20 tahun terakhir, pengobatan ala Rasulullah menjadi komoditi berharga demi meraih keuntungan ekonomi.
Tentunya diksi “ala Rasulullah” berhasil memancing emosi kesucian kaum muslimin lalu mengonsumsi produk dan jasa pengobatan tersebut. Maka tidaklah mengherankan jika pengobatan syar’i menjadi bisnis yang menjanjikan.
Benarkah pengobatan-pengobatan yang disebut ala Rasulullah itu bagian dari syariat? Apakah dengan demikian mengonsumsinya berkonsekuensi teologis dalam arti menegaskan teguhnya iman? Apakah semua itu sunnah Nabi?
Ibnu Khaldun punya komentar bernada minor tapi, menurut saya, proporsional terhadap persoalan ini dan tiada salahnya kita mempertimbangkan pandangannya. Pertanyaannya kemudian adalah: mengapa Ibnu Khaldun? Mengapa tidak merujuk pada pendapat para ahli syariat karena jelas ini masalah kesyariatan?
Abu Zayd Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun (1332-1406 M) lebih dikenal sebagai seorang sejarawan ketimbang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman. Di Barat dirinya begitu dihormati sebagai ilmuwan dan magnum opus-nya, Muqaddimah, menjadi salah satu rujukan penting dalam studi historiografi, antropologi dan sosiologi. Di kalangan muslim Ibnu Khaldun bahkan disebut-sebut sebagai Bapak Sosiologi mendahului Auguste Comte.
Kapasitas Ibnu Khaldun sebagai sejarawan dan sosiolog memberikan sudut pandang yang berbeda, sementara ahli ilmu syari’at akan cenderung berakhir pada keputusan bernada hitam-putih.
Bagi Ibnu Khaldun, sejarah adalah rentetan peristiwa yang saling terkait dan kehidupan sosial masyarakat beserta perubahan-perubahannya merupakan jejaring struktur yang juga saling terkait layaknya suatu organisme hidup.
Sejarah dan kehidupan sosial, karena itu, dapat dijelaskan secara rasional, termasuk klaim syar’i terhadap pengobatan-pengobatan tradisional yang disebut ala Rasulullah.
Komentar Ibnu Khaldun mengenai klaim pengobatan syar’i terhadapnya terdapat dalam Muqaddimah (saya merujuk kepada edisi terjemahan dari Pustaka Firdaus,2011: 676-677).
Ia menulis: “Pengobatan yang disebutkan dalam syari’at-syari’at agama (hadis-hadis Nabi) … sama sekali bukan wahyu.” Ini berarti Ibnu Khaldun menyatakan pengobatan ala Rasulullah bukan termasuk syariat, meskipun masih bisa disebut ala Rasulullah.
Ilmu kedokteran dan praktek pengobatan sudah dikenal dan lumrah di dalam masyarakat Arab klasik. Ibnu Khaldun bahkan mendedah bahwa tradisi pengobatan Arab berasal dari Yunani seraya menyebut Galenus atau Galen, yang karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menjadi rujukan para ahli kedokteran sesudahnya, termasuk dokter-dokter muslim.
Akan tetapi pengobatan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sebenarnya berasal dari orang-orang Badui yang telah hidup menetap, diwarisi para tetua suku mereka. Ibnu Khaldun mengatakan sebagian di antaranya benar, namun “tidak didasarkan pada hukum alami dan konformitas pengobatan menurut wataknya”.
Saya tidak mengatakan primitif, seperti dikatakan Philip K. Hitti (2010), tapi pengobatan-pengobatan yang dikonsumsi Nabi sebagaimana disebut dalam hadis-hadis jelas bukan pengobatan bersifat saintifik.
Dengan demikian, pengobatan ala Rasulullah merupakan hal biasa dalam kapasitas Nabi Muhammad sebagai seorang manusia Arab yang hidup di tengah kebudayaan masyarakatnya. “Materi-materi pengobatan itu disebutkan (dalam hadis-hadis) bukan untuk mengimplikasikan bahwa cara mempraktekkan pengobatan tersebut ditetapkan oleh syariat agama,” ungkap Ibnu Khaldun.
Lebih tegas lagi: “Muhammad Saw diutus untuk mengajarkan syariat-syariat agama. Beliau tidak diutus untuk mengajarkan kedokteran dan tidak pula adat kebiasaan lainnya.”
Lalu apakah keliru jika pengobatan-pengobatan itu disebut “ala Rasulullah”? Salahkah jika orang berbekam, mengonsumsi habbatussauda, ekstrak kurma, dan lain-lain dengan tujuan kesehatan dan dengan niat mengikuti sunnah Nabi? Saya katakan: tidak sepenuhnya keliru.
Apa yang dimaksud sunnah Nabi meliputi segala perilaku, tidak hanya berupa ujaran-ujaran lisan, tetapi juga perbuatan maupun pengakuan beliau. Karena itu, apapun yang dikatakan, dilakukan dan diakui beliau sebagai seorang utusan Tuhan dan paling memahami pesan-pesan-Nya menjadi patokan bagi pelaksanaan ajaran agama.
Hanya saja, tidak semua apa yang dilakukan Nabi serta-merta menjadi syariat agama, sebab pada diri Nabi sendiri terdapat dua kapasitas: sebagai utusan Tuhan di satu sisi dan sebagai manusia yang terikat ruang dan waktu di sisi yang lain.
Karena itu, diperlukan pemilahan mana sunnah Nabi yang menjadi syariat agama dan mana yang tidak. Pemilahan-pemilahan tersebut telah dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.
Meski begitu, mengikuti segala perilaku Nabi sebagai seorang manusia suci memberi rasa kedekatan dengan sosok Nabi dan apa yang disebut Nathan Soderblom, seorang ahli studi agama-agama, dengan “rasa kesucian” (lihat Mujiburrahman dalam Jurnal Kanz Philosophia, vol. 1, no. 2, 2011).
Bukankah ketika kita mencintai seseorang, sedikit-banyaknya kita akan meniru segala perilakunya, mulai dari tingkah laku sampai memakan makanan yang disukainya?
Dengan demikian, tidak sepenuhnya keliru orang yang mengonsumsi pengobatan ala Rasulullah dengan niat mengikuti sunnah Nabi, karena meniru Nabi melahirkan rasa kesucian, suatu elemen penting dalam beragama. Sama halnya ketika orang berobat dengan pengobatan modern, ada rasa kebanggaan dan dalam aspek tertentu rasa kesucian sebagai bagian dari masyarakat modern.
Kelirunya, jika merujuk pada Ibnu Khaldun, terletak pada klaim bahwa pengobatan ala Rasulullah itu bagian dari syariat agama. Dalam arti sederhana, mempraktekkannya mendapat pahala dan tidak mengonsumsinya dianggap sebagai gambaran lemahnya iman. Kebanggaan berlebihan semacam ini tidak dapat diterima, baik oleh ajaran agama maupun akal sehat.
Ibnu Khaldun menyatakan: “maka, tidak satupun dari pernyataan-pernyataan mengenai pengobatan yang terdapat dalam hadis-hadis sahih boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang disyariatkan. Yang boleh hanyalah apabila jenis medis semacam itu dipergunakan untuk memperoleh berkah Tuhan dan kebenaran ikatan keimanan, sehingga mempunyai pengaruh manfaat yang besar. Bagaimanapun, itu bukan termasuk kedokteran humoral, tetapi akibat dari keimanan yang tulus.”
Saya kira penilaian proporsional ala Ibnu Khaldun semacam ini juga dapat digunakan dalam memandang fenomena keberagamaan populis saat ini yang selalu ingin berperilaku serba syar’i.